Suara gesekan roda kereta api dengan rel perlahan memelan, berganti dengan riuh rendah suasana Stasiun Bandung yang tak pernah tidur.
Sabtu malam itu terasa berbeda bagi kami. Ada kelelahan yang menggelayut setelah hampir setengah hari duduk di gerbong kereta, namun ada pula percikan semangat yang tak padam.
Kedatangan kami ke Kota Kembang bukan sekadar pelesir, melainkan sebuah misi keluarga yang penuh rasa bangga: menghadiri prosesi wisuda keponakan tercinta di UIN Sunan Gunung Djati pada esok hari.
Keponakan kami, putri pertama dari kakak laki-laki saya—yang kini mengabdikan diri sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah di desanya—telah menyelesaikan babak penting dalam pendidikannya.
Namun, rasa haru dan bangga itu sejenak harus bersaing dengan kenyataan bahwa perut kami mulai berontak.
Rasa lapar yang tak bisa ditunda membawa kami menyusuri jalanan Bandung yang masih sibuk oleh kendaraan.
Kami memutuskan untuk menunda istirahat sejenak. Pencarian kami berakhir di sebuah warung penyetan sederhana di sudut kota pada Jumat malam (13/2/2026).
Warung itu tidaklah mewah, hanya berupa kedai kecil dengan tenda yang menaungi beberapa meja kayu panjang.
Namun, keramaian di dalamnya menjanjikan kehangatan.
Begitu kami melangkah masuk, aroma sambal terasi yang baru saja diulek langsung menyerbu indera penciuman, seolah menyapa dan mengundang kami untuk segera duduk.
Saya dan istri memesan ayam goreng, sementara kakak bersama keluarganya menjatuhkan pilihan pada lele dan tempe penyet.
Suasana warung yang riuh dengan obrolan pengunjung lain menciptakan harmoni tersendiri.
Tak lama kemudian, pesanan kami datang satu per satu, dibawa oleh seorang pelayan yang wajahnya dihiasi senyum ramah.
“Mangga, sok makanannya,” ujarnya dengan logat Sunda yang kental dan ramah sambil menyodorkan piring-piring berisi lauk yang masih mengepul, lengkap dengan gelas-gelas teh hangat.
Ucapan sederhana itu terasa begitu bersahabat, meruntuhkan sekat antara pendatang dan penduduk lokal.
Kami pun mulai menyantap hidangan dengan lahap.
Sambalnya memiliki tingkat pedas yang menggigit, berpadu sempurna dengan ayam goreng yang renyah dan lele yang gurih.
Di tengah kenikmatan itu, sebuah bisikan pelan dari istri saya memecah keheningan makan kami.
“Tehnya kok tawar ya, Yah? Nggak manis?” tanyanya heran.
Putri saya, yang memang hobi mengonsumsi minuman manis, juga melontarkan kebingungan yang sama.
Mereka juga mendapati nasi goreng yang dipesan terasa sangat pedas, sebuah karakteristik kuliner Sunda yang memang jarang berkompromi dengan rasa cabai.
Melihat raut bingung mereka, saya tersenyum kecil.
Ingatan saya seketika melayang ke masa 23 tahun silam, sekitar tahun 2003.
Saat itu, saya masih muda dan bertugas sebagai surveyor di wilayah Jawa Barat dan Banten untuk sebuah perusahaan semen.
Selama berbulan-bulan, saya hidup berpindah dari satu warung kecil ke warung lainnya.
Di sanalah saya pertama kali belajar tentang sebuah etika tak tertulis di tanah Pasundan.
Di wilayah ini, jika kita hanya menyebut kata “teh” saat memesan, maka secara otomatis yang akan tersaji adalah teh tawar hangat.
Bagi masyarakat Sunda, teh tawar adalah penetralisir lemak dan rasa pedas setelah makan, sekaligus simbol keramahan yang diberikan secara cuma-cuma.
Jika ingin rasa yang manis, kita harus secara eksplisit mengatakan “teh manis”.
Kebiasaan ini merupakan antitesis dari budaya di Jawa Timur, tempat saya dibesarkan, di mana teh yang disajikan biasanya sudah manis kecuali kita meminta sebaliknya.
Sambil menikmati sisa ayam goreng, saya menjelaskan perbedaan budaya kecil ini kepada istri dan anak-anak.
Istri saya manggut-manggut mengerti, lalu tertawa kecil menyadari kekeliruannya.
Ia segera memanggil penjual untuk meminta tambahan gula.
Momen sederhana ini, meski tampak sepele, sebenarnya adalah pelajaran besar tentang kehidupan.
Saya menyadari kembali betapa pentingnya memahami budaya dan adat istiadat setempat.
Belajar budaya bukan hanya soal menghafal tarian daerah atau aturan resmi dalam upacara adat.
Budaya hadir dalam detail terkecil keseharian: cara berbicara, pilihan kata, selera rasa, hingga cara menyajikan segelas minuman.
Dengan memahaminya, kita tidak hanya terhindar dari salah paham, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada “tuan rumah” tempat kita berpijak.
Pepatah lama mengatakan, “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”
Kalimat itu terasa sangat relevan malam itu.
Kita boleh membawa identitas dan kebiasaan dari kampung halaman, namun saat berada di tempat lain, sudah sepantasnya kita menyesuaikan diri.
Bukan untuk menghilangkan jati diri, melainkan untuk memperkaya perspektif dan menghargai perbedaan.
Pengalaman segelas teh tawar ini mengingatkan saya bahwa keberagaman Indonesia bukan hanya tentang suku-suku besar, tetapi tentang detail-detail unik di setiap sudut daerahnya.
Justru di sanalah keindahannya. Akhirnya, kami meninggalkan warung itu dengan perut kenyang dan hati yang damai.
Malam di Bandung itu memberikan pelajaran berharga: bahwa memahami budaya adalah kunci untuk bersikap arif dalam setiap langkah perjalanan hidup.***













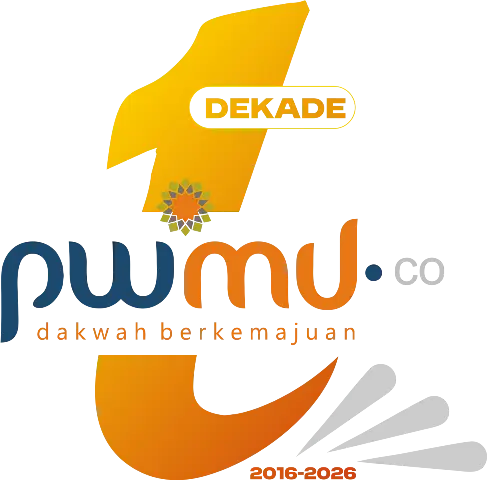

0 Tanggapan
Empty Comments