Menjelang Ramadan, lembaga pendidikan kembali menjadi arena negosiasi antara tuntutan kurikulum, stamina fisik siswa yang berpuasa, serta ekspektasi keluarga agar bulan suci bertransformasi menjadi laboratorium pendidikan iman.
Polemik ini kerap berulang dengan pola serupa: haruskah sekolah meliburkan siswa secara total, sekadar memangkas jam pelajaran, atau tetap beroperasi secara reguler?
Menilik rekam jejak sejarah, wacana ini bukanlah komoditas baru.
Indonesia pernah menerapkan kebijakan radikal: meliburkan sekolah selama satu bulan penuh.
Museum Kepresidenan mencatat, pada 1999—tahun pertama kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—sekolah diliburkan sebulan penuh dengan imbauan agar masa tersebut dioptimalkan untuk pesantren kilat.
Kebijakan ini menegaskan pengakuan negara bahwa ritme kognitif dan spiritual di bulan puasa memang memerlukan perlakuan berbeda.
Jejak yang lebih lama bahkan muncul pada era kolonial.
Merujuk catatan Historia, pemerintah Hindia Belanda meliburkan sekolah binaan—mulai dari HIS, HBS, hingga AMS—selama Ramadan hingga pasca-Lebaran dengan durasi sekitar 39 hari.
Terlepas dari apa pun motif politik di baliknya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kalender pendidikan pernah disusun dengan mempertimbangkan realitas sosiokultural mayoritas masyarakat.
Lantas, mengapa paradigma tersebut bergeser?
Di era Orde Baru, restriksi libur Ramadan menjadi kontroversi tajam.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef, memandang libur sebulan penuh sebagai bentuk “pembodohan” warisan kolonial yang menghambat akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan.
Melalui SK Mendikbud No. 0211/U/1978, libur dipangkas drastis menjadi hanya 10 hari kerja.
Muncul logika baru: puasa tidak boleh mendegradasi mutu belajar; justru harus menjadi katalisator disiplin dan ketangguhan mental.
Dalam konteks ini, kita harus objektif: kedua kubu argumen memiliki pijakan yang sama-sama valid.
Ramadan adalah momentum transendental yang mengubah pola tidur, energi fisik, dan dinamika keluarga.
Namun, pendidikan juga memerlukan konsistensi, terutama di tengah kian melebarnya kesenjangan mutu sekolah.
Maka, diskursus yang lebih produktif bukanlah “libur atau tidak”, melainkan bagaimana mensinergikan kualitas belajar dan kualitas beribadah secara simultan.
Pelajaran pertama adalah soal adaptasi ritme.
Sekolah yang memaksakan standar normal tanpa penyesuaian sering kali terjebak dalam disfungsi ganda: siswa kelelahan dan materi pelajaran gagal terabsorpsi.
Sebaliknya, sekolah yang melonggarkan jadwal tanpa desain program yang matang berisiko menciptakan “vakum aktivitas” yang nir-manfaat.
Warisan Gus Dur menarik karena ia merelevansikan libur dengan program substantif: tadarus, kajian reflektif, hingga aksi sosial.
Intinya, jeda bukan berarti tanpa arah.
Pelajaran kedua menyangkut pergeseran fokus.
Pendidikan di bulan Ramadan tidak harus identik dengan reduksi target akademik, melainkan menggeser fokus..
Dalam tradisi Islam, wahyu perdana adalah Iqra (bacalah).
Ramadan seharusnya menjadi musim literasi: mengintegrasikan pembacaan Al-Qur’an dengan tradisi menelaah buku, menulis refleksi, dan berdialektika.
Di lingkungan Muhammadiyah, spirit tajdid mendorong pengelolaan ibadah dan ilmu sebagai satu tarikan napas “beragama yang berkemajuan”.
Pesantren kilat tidak boleh berhenti pada seremoni formal, tetapi harus mengasah akhlak dan ketajaman berpikir.
Pelajaran ketiga adalah reklamasi peran keluarga.
SK Mendikbud tahun 1978 mengisyaratkan bahwa libur adalah masa “beralihnya konsentrasi pendidikan” dari sekolah ke ranah domestik dan sosial.
Ramadan membuka ruang bagi orang tua untuk mengukuhkan perannya: membangun disiplin sahur, memoderasi penggunaan gawai, serta menginternalisasi etika sosial melalui filantropi.
Sekolah dapat berperan sebagai fasilitator melalui panduan jurnal amalan atau proyek pengabdian masyarakat yang terukur.
Oleh karena itu, kebijakan Ramadan yang paling ideal adalah yang bersifat fleksibel namun tetap akuntabel.
Sejarah membuktikan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan sering kali terdesentralisasi.
Pelajaran praktisnya jelas: jangan menunggu kebijakan seragam dari pusat, melainkan rancanglah arsitektur pembelajaran yang adaptif terhadap berbagai skenario.
Jam instruksional bisa disesuaikan, aktivitas fisik yang menguras energi dikurangi, dan evaluasi akademik dikemas lebih padat, sementara muatan karakter dipertebal.
Sebagai contoh, pekan pertama difokuskan pada pembiasaan (salat berjamaah, adab puasa, manajemen waktu); pekan kedua pada literasi dan tadabur; pekan ketiga pada proyek empati sosial (bakti lingkungan, paket berbagi, kunjungan panti); dan pekan terakhir pada refleksi Idulfitri.
Guru pun memerlukan ruang untuk menjaga stabilitas emosional dan spiritualnya, karena kualitas pendidikan di bulan ini sangat bergantung pada keteladanan pendidik.
Menjelang Ramadan, mari berhenti memulai debat dari titik nol.
Dinamika sejarah mengajarkan bahwa yang kita cari bukan format tunggal yang kaku, melainkan cara paling presisi dalam membaca kebutuhan pertumbuhan anak.
Ramadan adalah bulan pendidikan.
Tugas sekolah adalah memastikan simfoni belajar selaras dengan ritme ibadah, agar siswa tidak sekadar “bertahan” menahan lapar, tetapi benar-benar tumbuh: ilmunya bertambah, akhlaknya menguat, dan empatinya menajam.***













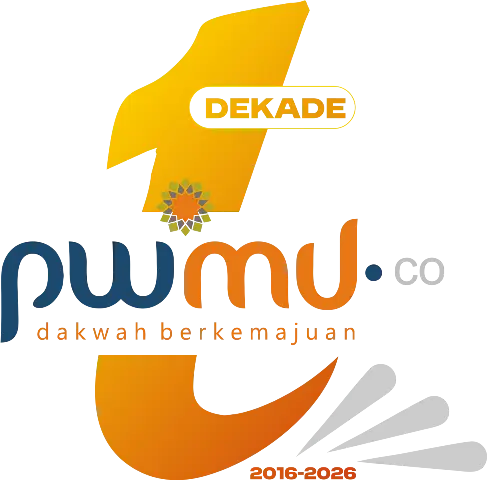

0 Tanggapan
Empty Comments