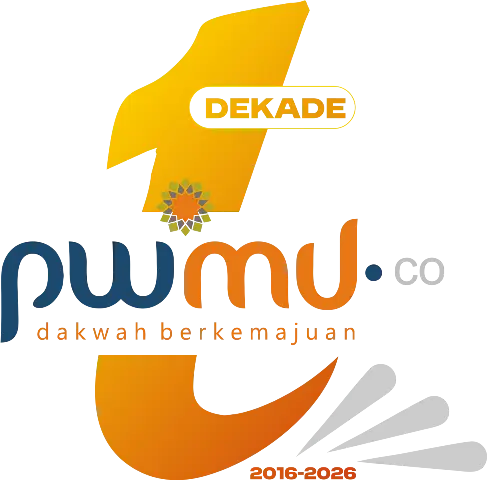Setiap ayat Al-Qur’an yang kita baca selalu menyadarkan bahwa Islam merupakan agama yang datang langsung dari Allah, bukan hasil kreativitas olah pikir manusia. Karena itu, Islam adalah agama yang suci, sempurna, dan abadi. Inilah yang kita sebut sebagai “Islam Tuhan” karena turun dari langit (Tuhan.red) untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia.
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku Cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku ridhoi Islam itu menjadi agamamu…” (QS. Al-Maidah [5]: 3)
Di alam dunia, ketika ajaran ini harus berinteraksi dengan pikiran, budaya, dan kepentingan manusia, maka lahirlah “Islam Manusia”. Islam ini menjadi Islam yang dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh umat manusia. Islam dalam wujud yang kedua ini bisa menjadi indah dan membumi, tetapi juga bisa ternoda oleh ego, fanatisme, atau ketidaktahuan.
Sejarah membuktikan, terkadang jarak antara “Islam Tuhan dan Islam Manusia” terasa begitu sangat dekat. Tapi pada situasi yang berbeda bisa pula terasa sangat jauh. Ada masa ketika umat menjadi teladan dunia — karena sukses mewujudkan keadilan, menebar rahmat, dan memajukan peradaban. Tapi ada pula masa ketika umat justru menjadi sumber persoalan, sumber ketakutan dan perpecahan. Tentu hal tersebut bukan karena ajaran Islamnya, melainkan karena perilaku manusianya.
Menyikapi realita terkait adanya dua wajah Islam tersebut (Islam Tuhan dan Islam Manusia) membutuhkan kesadaran kita agar mampu rendah hati. Sebab, seringkali yang kita membela dengan penuh emosi. Padahal yang kita bela sesungguhnya bukan Islam Tuhan yang murni, melainkan hanya Islam Manusia hasil penafsiran sendiri — yang memiliki potensi benar dan keliru yang sama.
Para ulama besar, sejak era klasik hingga kontemporer, senantiasa mengingatkan bahwa memahami Islam memerlukan ilmu, kejernihan hati, dan sikap terbuka. Imam Asy-Syafi’i, misalnya, pernah berkata: “Pendapatku benar, namun mungkin salah. Pendapat orang lain salah, namun mungkin benar.” Semestinya spirit ini dapat menjaga perbedaan tafsir agar selalu dalam koridor adab dan ukhuwah.
Era media sosial seperti saat ini, ruang tafsir sering berubah menjadi medan perang opini. Kepentingan politik atau kelompok dibungkus dengan simbol-simbol agama. Saling mengklaim kebenaran menjadi suatu tradisi atau kebiasaan, dan saling menyesatkan menjadi retorika yang dianggap wajar. Akibatnya, wajah Islam Manusia di ruang publik seringkali menjadi tampak kusam karena penuh kemarahan dan saling curiga.
Menjembatani Langit dan Bumi
Tanggung Jawab utama umat Islam saat ini adalah memendekkan rentang atau kesenjangan antara Islam Tuhan dan Islam Manusia. Kita perlu berupaya menjadikan perilaku kita selalu bercermin pada nilai-nilai wahyu, sehingga Islam yang dipraktikkan di muka bumi ini mendekati cahaya yang turun dari langit.
Ada tiga langkah penting untuk memendekkan kesenjangan tersebut, yaitu: pertama, pendalaman ilmu. Islam tidak cukup dijalankan dengan semangat saja, tetapi harus berlandaskan pemahaman yang benar. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama” (HR. Bukhari-Muslim).
Kedua, keteladanan akhlak. Rasulullah SAW menjadi jelmaan sempurna dari Al-Qur’an. Beliau tidak hanya mengajarkan ibadah mahdhah, tetapi juga menjadi teladan dalam menebarkan kasih sayang kepada siapapun, tetangga yang berbeda agama. Tidak hanya memerintahkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, tetapi juga memaafkan dengan kemuliaan hati.
Ketiga, kesadaran sosial. Islam Tuhan selalu berpihak kepada keadilan dan keberpihakan terhadap yang lemah. Ironisnya, tidak jarang praktik keberagamaan kita justru memarginalkan orang miskin, mengabaikan anak yatim, atau membiarkan korupsi. Pendek kata, kita sedang menghadapi kondisi yang menjauh dari Islam yang sejati.
Cermin untuk Indonesia
Indonesia adalah rumah bagi umat Muslim terbesar di dunia. Karena itu, sebagai umat Muslim Indonesia, kita memikul amanah besar untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Karena dunia tidak menilai Islam dari isi teks kitab sucinya, tetapi dari perilaku umat Islam yang menjadi penganutnya.
Korupsi, intoleransi, dan kekerasan secara nyata tidak ada dalam ajaran Islam Tuhan. Semua itu merupakan hasil distorsi dari Islam Manusia yang lemah dalam integritas. Jika kita ingin dunia merasakan kemuliaan Islam, maka kita sebagai umat Islam harus memulainya dari pembenahan diri — mulai dari simbol ke substansi, dari klaim kebenaran menuju ramah terhadap perbedaan, dari ibadah ritual menuju ibadah sosial yang nyata.
Seorang ulama kontemporer pernah mengingatkan, “Jangan biarkan orang membenci Islam karena perilaku kita. Biarlah mereka mencintai Islam karena akhlak kita.”
Islam Tuhan adalah cahaya dari langit yang tidak pernah redup. Islam Manusia adalah pantulan cermin di bumi. Maka jernih atau buramnya tergantung pada hati dan perilaku umat. Jika kita ingin cahaya itu memancar indah, maka cermin itu harus dibersihkan dari debu ego, kepentingan, dan kebodohan.
Ketika Islam turun dari langit ke hati manusia, ia akan menjadi rahmat yang dirasakan semua makhluk. Bukan hanya slogan di bibir atau simbol di bendera semata. Itulah misi besar kita: menghadirkan Islam yang benar-benar hidup, tidak hanya didalam teks book, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. ***