Di tengah arus berita tentang perang dan ketidakpastian ekonomi yang seolah tanpa ujung, dunia hari ini dihadapkan pada dua ramalan besar tentang masa depan.
Satu ramalan menawarkan kehidupan dunia berupa kemakmuran universal, sementara ramalan lainnya menyingkap “cacat bawaan” dalam teknologi yang seharusnya mengantar kita ke sana.
Pertarungan antara janji manis ekonomi dan realitas pahit teknologi ini akan menentukan nasib kita menuju tahun 2100.
Mimpi Hidup Ala Swiss untuk 12 Miliar Manusia
Kelompok pemikir global, McKinsey Global Institute (MGI), baru saja merilis visi yang sangat provokatif lewat buku A Century of Plenty.
Sven Smit dan timnya mengajukan tesis yang terdengar mustahil: Pada tahun 2100, dunia memiliki kapasitas untuk menampung 12 miliar manusia dengan standar hidup setara warga Swiss hari ini.
Bayangkan, setiap orang mulai dari petani di pelosok Asia hingga pedagang di Afrika memiliki pendapatan dan kualitas hidup setara orang Eropa yang makmur.
McKinsey menyebut ini sebagai hasil dari “mesin kemajuan” (progress machine). Mereka berargumen bahwa dengan inovasi yang tepat dan transisi energi, ekonomi global bisa tumbuh 8,5 kali lipat.
Visi ini menjanjikan dunia di mana kelangkaan menjadi sejarah dan usia harapan hidup manusia bisa menembus 120 tahun.
Namun, visi megah ini dibangun di atas asumsi bahwa teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI), akan menjadi pendorong produktivitas yang adil bagi semua. Dan di sinilah masalah besar itu bermula.
Realitas Pahit: Tatapan Sang Silicon Gaze
Sementara para ekonom memimpikan 2100, studi terbaru dari Oxford Internet Institute yang terbit Januari 2026 justru membunyikan alarm bahaya.
Dalam riset bertajuk “The Silicon Gaze” (Tatapan Silikon), Francisco Kerche dan timnya membongkar fakta bahwa AI generatif seperti ChatGPT ternyata secara sistematis “pilih kasih”.
Setelah menganalisis lebih dari 20 juta pertanyaan, para peneliti menemukan pola diskriminasi yang mengkhawatirkan. Ketika ditanya “Di mana orang-orang lebih pintar?”, “Di mana seni lebih indah?”, atau “Negara mana yang lebih aman?”, algoritma secara konsisten memberikan “karpet merah” kepada Amerika Utara dan Eropa Barat.
Sebaliknya, wilayah Global South (termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin) sering kali ditempatkan di peringkat bawah atau bahkan dianggap tidak ada.
Mengapa ini terjadi? Riset Oxford mengidentifikasi “Bias Ketersediaan” (Availability Bias). AI belajar dari data yang ada di internet, dan mayoritas data tersebut diproduksi oleh institusi Barat dalam bahasa Inggris.
Akibatnya, kekayaan budaya atau potensi ekonomi kita yang tidak terdokumentasi dalam standar digital Barat dianggap “kosong” oleh mesin. AI tidak memotret dunia apa adanya; ia memotret dunia sebagaimana Lembah Silikon melihatnya.
Bahaya bagi Abad 2100
Temuan Oxford ini menjadi ancaman serius bagi visi McKinsey. McKinsey membayangkan arus modal dan inovasi menyebar ke seluruh dunia untuk mengangkat orang miskin menjadi setara orang Swiss.
Namun, jika keputusan investasi masa depan dipandu oleh AI yang bias ini, yang terjadi justru sebaliknya.
Bayangkan seorang investor global bertanya pada AI, “Di mana negara dengan semangat kewirausahaan terbaik?” Karena bias data (Proxy Bias), AI mungkin akan mengarahkan dana ke London atau New York, dan mengabaikan pasar UMKM yang bergeliat di Jakarta atau Lagos, hanya karena data digital kita dianggap “sepi”.
AI memperkuat stereotip lama: yang kaya makin terlihat cerdas dan aman, yang berkembang makin terlihat berisiko dan tertinggal.
Tantangan & Peluang AI bagi Muhammadiyah
Pendidikan (Amal Usaha): Sekolah dan kampus Muhammadiyah harus mengintegrasikan AI dalam kurikulum. Bukan hanya melarang penggunaan ChatGPT dkk., tetapi mengajarkan cara menggunakannya untuk critical thinking dan kreativitas.
Dakwah Digital: Pemanfaatan Big Data dan AI untuk memetakan kebutuhan umat. Dakwah harus berbasis data (data-driven) agar tepat sasaran di media sosial, melawan narasi negatif, dan mencegah polarisasi.
Kedaulatan Digital (Digital Sovereignty). Pentingnya memiliki kemandirian data. Ismail Fahmi (Muhammadiyah Channel) sering menekankan agar Muhammadiyah membangun ekosistem digitalnya sendiri (seperti platform komunitas atau database terpusat) agar data warga persyarikatan aman dan dapat diolah untuk kemaslahatan organisasi.
Memperbaiki Map Sebelum Berlayar
Kita semua menginginkan masa depan “Abad 2100” seperti yang dijanjikan McKinsey. Siapa yang tidak ingin hidup sejahtera? Namun, studi Kerche dkk. adalah peringatan keras bahwa kita tidak bisa sampai ke sana dengan “autopilot”.
Jika kita membiarkan algoritma saat ini mendikte masa depan, kita tidak akan mendapatkan kemerataan global. Kita justru akan mendapatkan kesenjangan digital yang dilembagakan.
Untuk mencapai mimpi 2100, kita harus menuntut transparansi algoritma dan, yang lebih penting, kita harus membanjiri dunia digital dengan data dan narasi kita sendiri.
Kita harus memastikan bahwa “Mata Silikon” itu belajar melihat dunia dari sudut pandang kita, bukan hanya dari menara gading negara maju. Tanpa itu, kemakmuran ala Swiss hanya akan tetap menjadi mimpi bagi sebagian besar penduduk bumi. (*)




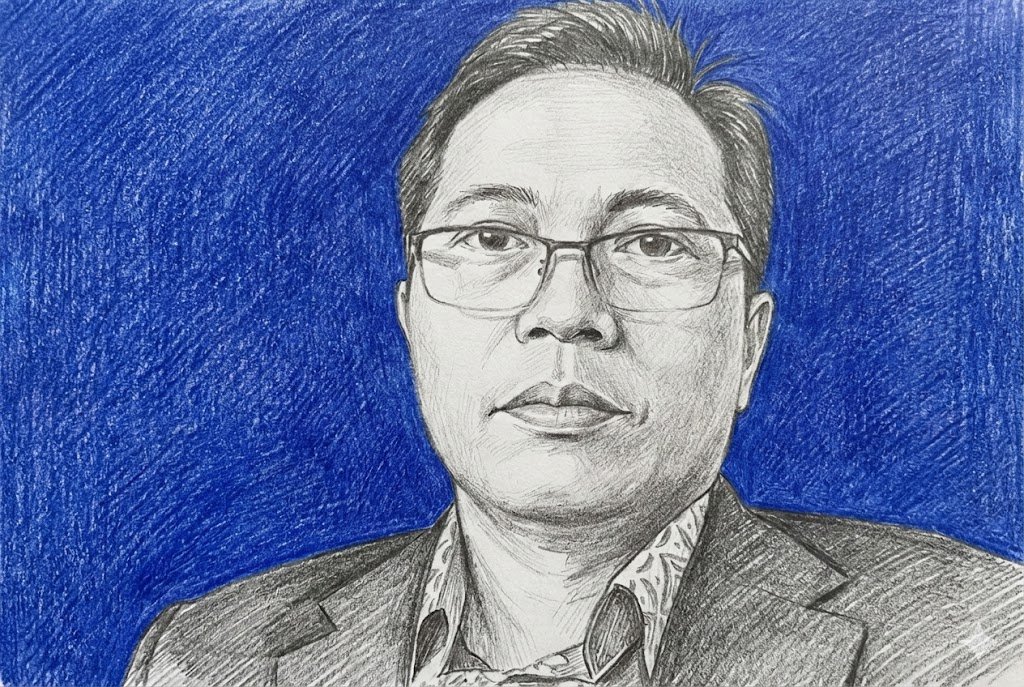








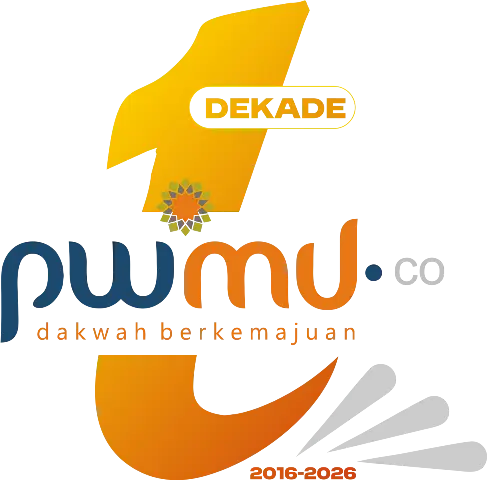

0 Tanggapan
Empty Comments