Gelombang protes rakyat pada Senin (25/8/2025) di depan kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sejatinya bukan aksi jalanan biasa. Demonstrasi massa itu lahir dari akumulasi kekecewaan rakyat yang mengendap lama.
Kebijakan mengenai tambahan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR — padahal penghasilan mereka per bulan sudah mencapai rata-rata Rp 230 juta — menjadi penyulut api amarah rakyat.
Bagaimana mungkin, di tengah rakyat yang menjerit karena sedang menghadapi kenaikan harga pangan, sulitnya mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli — para wakil rakyat justru menambah fasilitas mewah untuk diri mereka sendiri?
Fenomena tersebut semakin mempertontonkan adanya kesenjangan yang semakin melebar, antara yang terjadi pada rakyat dengan yang anggota DPR dapatkan.
Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menguatkan sinyal tentang adanya ketidakadilan tersebut.
Dengan pendapatan sekitar Rp 2,8 miliar per tahun, setiap anggota DPR sebenarnya sudah masuk jajaran elite ekonomi.
Ironisnya, pendapatan atau gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan kinerja maupun citra publik mereka.
Sebaliknya, rakyat justru menilai DPR yang semakin menjauh dari tugas mulianya sebagai representasi aspirasi rakyat.
Karena itu, wacana pembubaran DPR yang sebelumnya hanya menggaung di media sosial (medsos) pun menjelma menjadi tuntutan serius. Melalui demonstrasi besar-besaran yang penuh darah dan benturan.
Lagi-lagi, di sini memunculkan sebuah paradoks. Secara konstitusional, pembubaran DPR bukanlah hal yang berlaku secara sepihak. Pasal 7 C UUD 1945 telah menegaskan bahwa presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
Aturan ini lahir dari sejarah panjang tarik-menarik kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR-GR — yang kala itu dipandang sebagai jalan keluar atas ketidakstabilan politik.
Dekade berikutnya, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencoba mengulang langkah serupa melalui Dekrit Presiden tahun 2001, dengan membekukan DPR dan MPR.
Namun, langkah Gus Dur tersebut dianggap inkonstitusional dan berujung pada pemakzulan dirinya. Bermula dari itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambahkan pasal tegas dalam amandemen UUD 1945 agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Dengan demikian, meski rakyat begitu nyaring meneriakkan tuntutan pembubaran DPR, secara hukum teriakan tuntutan itu tidak mungkin berhasil melalui tangan Presiden.
Kedudukan DPR begitu kuat dan sejajar dengan Presiden. Mekanisme check and balances dalam sistem presidensial memang dirancang agar tidak ada lembaga yang bisa dengan mudah menyingkirkan yang lain.
Bahkan, konflik politik sekeras apa pun harus ditempuh melalui jalur konstitusional, bukan dekrit atau langkah sepihak.
Pertanyaannya, “apakah kekuatan konstitusi seperti DPR bebas dari krisis legitimasi?” Jawabnya jelas “tidak!”.
Maka, saat DPR berupaya memanfaatkan posisinya yang tak tergoyahkan untuk menumpuk privilese, saat itulah legitimasi politiknya menjadi runtuh.
Kekuasaan tanpa legitimasi ibarat bangunan megah tanpa pondasi — tampak kokoh, tetapi sewaktu-waktu bisa runtuh karena terjangan badai.
Demonstrasi besar hanyalah gejala awal dari krisis kepercayaan yang lebih dalam. Konstitusi memang menjamin DPR tidak bisa dibubarkan, tetapi konstitusi juga menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Jika DPR kehilangan kepercayaan rakyat, maka secara moral lembaga tersebut sudah lumpuh. Meski secara hukum masih berdiri tegak.
Inilah titik rawan demokrasi kita. Ketika hukum dan konstitusi melindungi keberadaan lembaga, dan legitimasi publik terhadap lembaga terus terkikis.
Jalan keluarnya, menurut saya, bukan pada pembubaran DPR. Ketika secara hukum upaya pembubaran itu tidak mungkin, maka perlu adanya perombakan mendasar terhadap kultur politik dan tata kelola lembaga legislatif.
Transparansi anggaran, pemangkasan tunjangan yang tidak rasional, serta mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat harus menjadi tuntutan utama.
Reformasi sistem pemilu agar lahir wakil-wakil rakyat yang benar-benar dekat dengan rakyat mutlak diperlukan. Tanpa perubahan substansial ini, DPR hanya akan menjadi simbol kekuasaan kosong yang semakin dibenci publik.
DPR memang sesuai konstitusi tidak mungkin bisa dibubarkan. Tetapi bukan berarti bisa terus-menerus berjalan di atas jurang krisis legitimasi. Suara rakyat yang mengguncang dalam demonstrasi di bulan Agustus menjadi alarm keras bahwa lembaga ini kehilangan arah.
Jika DPR tidak segera berbenah, maka ia eksis hanya secara hukum (de jure) sebagai lembaga, tetapi secara moral sudah mati — di mata rakyat. Itulah paradoks paling berbahaya dalam demokrasi: ketika wakil rakyat tidak lagi mewakili rakyat.***













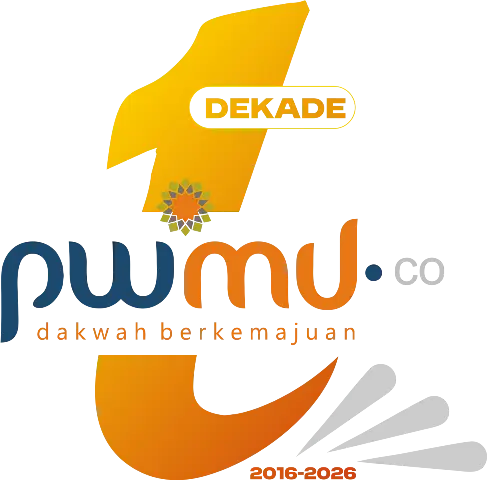

0 Tanggapan
Empty Comments