Di tengah kebisingan ruang publik, dakwah kerap terjebak dalam kompetisi retorika, adu klaim kebenaran, dan pencitraan moral.
Ukuran keberhasilan sering direduksi menjadi viralitas, jumlah pengikut, atau kekuatan narasi, sementara dimensi paling mendasar niat lillāh justru terpinggirkan.
Padahal, dalam perspektif Islam, nilai amal tidak ditentukan oleh seberapa keras ia terdengar, melainkan oleh sejauh mana ia ikhlas dan benar di hadapan Allah.
Di sinilah Surah Al-‘Ashr menghadirkan kerangka teologi yang sederhana namun radikal: keselamatan bukan proyek ego individual, melainkan kerja kolektif yang dibangun di atas iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran.
Surah Al-‘Ashr tidak berbicara tentang kehebatan retorika, melainkan tentang struktur etika keberagamaan.
Iman bukan sekadar afirmasi teologis, tetapi kesadaran eksistensial akan keterbatasan manusia di hadapan Allah. Amal saleh bukan performa simbolik, melainkan praksis nyata yang berdampak sosial.
Tawāshau bil-haqq dan tawāshau bis-shabr menegaskan bahwa dakwah adalah proses dialogis, bukan monolog penghakiman. Kebenaran disampaikan dengan kesabaran, bukan dengan superioritas moral.
Nabi Muhammad saw melalui Sunnah Maqbullah menegaskan prinsip ini secara konsisten. Dalam hadis sahih, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap amal tergantung niatnya. Ini bukan pernyataan spiritual yang abstrak, tetapi fondasi etika publik.
Dakwah yang kehilangan orientasi lillāh akan mudah tergelincir menjadi instrumen dominasi simbolik mengoreksi dengan merendahkan, mengajak dengan menghakimi, dan menasihati dengan merasa paling.
Sebaliknya, dakwah yang berangkat dari lillāh melahirkan kerendahan hati epistemik: kesadaran bahwa kebenaran adalah amanah, bukan trofi.
Teologi Al-‘Ashr juga mengajarkan bahwa keselamatan bersifat kolektif. Tidak ada keselamatan individual yang dibangun di atas runtuhnya martabat orang lain.
Prinsip tawāshau meniscayakan relasi horizontal yang setara: saling, bukan sepihak. Dalam konteks ini, dakwah tanpa penghakiman bukan berarti relativisme moral, tetapi peneguhan adab.
Islam tidak melarang kritik, namun mengikatnya dengan etika. Kritik yang berangkat dari ego akan melahirkan polarisasi; kritik yang berangkat dari lillāh akan melahirkan perbaikan.
Fenomena dakwah kontemporer sering kali terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai moral exhibitionism: kesalehan yang dipamerkan, bukan dihayati.
Al-‘Ashr justru mengajarkan kesalehan yang sunyi namun berdaya. Nabi Muhammamd saw bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi hati dan amal.
Ini adalah kritik teologis yang tajam terhadap budaya dakwah yang terlalu menekankan penampilan dan narasi, namun miskin keteladanan.
Menempatkan lillāh sebelum retorika berarti mengembalikan dakwah pada hakikatnya sebagai ibadah, bukan panggung. Ia menuntut kejujuran niat, kedalaman ilmu, dan kedewasaan akhlak.
Dalam kerangka Al-‘Ashr, dakwah bukan sekadar menyelamatkan orang lain, tetapi upaya bersama agar tidak termasuk golongan yang merugi.
Di sinilah dakwah menemukan wajahnya yang paling autentik: tidak menghakimi, tidak mengklaim paling benar, tetapi terus mengajak dengan hikmah, menasihati dengan sabar, dan berjalan bersama menuju rida Allah. (*)













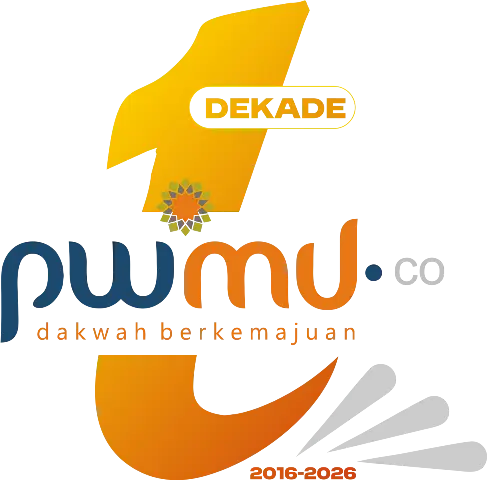

0 Tanggapan
Empty Comments