Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, baik antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Salafi, maupun kelompok Islam lainnya bukanlah fenomena baru. Perbedaan ini telah ada sejak masa awal Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika keilmuan serta praktik keberagamaan.
Persoalannya bukan pada adanya perbedaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana umat Islam menyikapinya: apakah dengan kedewasaan, atau justru dengan prasangka dan konflik.
Sebagai seorang yang berlatar Muhammadiyah, penulis memandang bahwa perbedaan adalah keniscayaan intelektual, sementara persatuan adalah kewajiban teologis dan sosial.
Allah SWT secara tegas menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak-Nya:
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
“Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.” (QS. Hud: 118)
Ayat ini menegaskan satu prinsip mendasar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan beragama: perbedaan adalah kehendak Allah, bukan kecelakaan sejarah. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi-Nya menjadikan manusia seragam dalam pemahaman, praktik, dan cara pandang. Namun Allah justru membiarkan bahkan menetapkan adanya perbedaan.
Dalam konteks umat Islam, ayat ini memberi pesan penting bahwa ikhtilaf bukan tanda kegagalan beragama, melainkan konsekuensi dari kemampuan manusia berpikir, menalar, dan berijtihad.
Perbedaan pendapat dalam fikih, metode dakwah, maupun pendekatan keagamaan: seperti yang terjadi antara Muhammadiyah, NU, Salafi, LDII, dan kelompok Islam lainnya berada dalam ruang yang dibenarkan selama bersandar pada dalil dan niat mencari kebenaran.
Bagi Muhammadiyah, ayat ini selaras dengan semangat tajdid dan ijtihad. Perbedaan tidak dihindari, tetapi dikelola secara ilmiah dan beradab. Yang menjadi masalah bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan ketika perbedaan berubah menjadi klaim kebenaran tunggal, saling menyesatkan, bahkan memutus ukhuwah.
Ayat ini juga mengingatkan bahwa tugas manusia bukan menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya dengan akhlak. Sebab Allah tidak memerintahkan keseragaman, tetapi memerintahkan persaudaraan. Karena itu, menyikapi ikhtilaf dengan kebencian dan permusuhan justru bertentangan dengan hikmah ayat ini.
Dengan memahami QS. Hud: 118 secara utuh, umat Islam semestinya lebih dewasa: teguh dalam keyakinan, lapang dalam perbedaan, dan kokoh dalam persatuan. Perbedaan adalah ruang ujian, sementara ukhuwah adalah tanggung jawab bersama.
***
Namun Al-Qur’an juga memberi rambu yang sangat jelas:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali Imran: 103)
Dalam firman Allah di atas sudah jelas bahwa perintah Allah kepada seluruh umat Islam agar menjadikan ajaran-Nya sebagai pegangan bersama dan tidak terjebak dalam perpecahan.
“Berpegang teguh pada tali Allah” dimaknai oleh para ulama sebagai berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama dalam beragama.
Ayat ini menegaskan bahwa titik temu umat Islam bukanlah pada keseragaman pandangan atau praktik, melainkan pada kesamaan akidah, tujuan, dan komitmen terhadap nilai-nilai ilahi.
Penegasan kata “semuanya” menunjukkan bahwa perintah ini bersifat kolektif, berlaku bagi seluruh umat tanpa kecuali, sehingga tidak dibenarkan adanya sikap eksklusif yang merasa paling benar dan merendahkan kelompok lain.
Sementara larangan “janganlah kamu bercerai-berai” bukan berarti meniadakan perbedaan pendapat, karena ikhtilaf merupakan keniscayaan, tetapi melarang perpecahan yang melahirkan permusuhan, saling menyesatkan, dan memutus ukhuwah.
Ayat ini juga mengingatkan umat Islam akan nikmat persatuan yang dianugerahkan Allah setelah sebelumnya hidup dalam konflik, sehingga persatuan harus dijaga sebagai amanah keimanan.
Maka QS. Ali ‘Imran ayat 103 mengajarkan bahwa umat Islam boleh berbeda dalam ijtihad dan praktik cabang agama, tetapi wajib bersatu dalam akidah, akhlak, dan persaudaraan.
***
Fakta Empiris: Perbedaan yang Nyata di Tengah Umat
Secara faktual, perbedaan antar ormas Islam di Indonesia tampak dalam banyak hal:
Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri, seperti yang hampir setiap tahun terjadi antara metode hisab Muhammadiyah dan rukyat NU.
Praktik ibadah, misalnya qunut Subuh, jumlah rakaat tarawih, tahlilan, atau peringatan hari-hari besar Islam.
Pendekatan dakwah, di mana Salafi cenderung tekstual dan puritan, NU kultural-tradisional, Muhammadiyah tajdid dan rasional, serta LDII dengan sistem pembinaan internalnya.
Namun fakta lain yang sering luput adalah: di banyak desa dan kota, warga Muhammadiyah, NU, Salafi, dan LDII hidup berdampingan secara damai, bergotong royong dalam urusan sosial, kebencanaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa konflik bukan keniscayaan dari perbedaan.
Pandangan Muhammadiyah: Ikhtilaf Harus Ilmiah dan Beradab
Muhammadiyah sejak awal berdiri menempatkan perbedaan pendapat sebagai bagian dari ijtihad. KH Ahmad Dahlan sendiri dikenal terbuka terhadap kritik dan dialog, bahkan berani mengoreksi praktik keagamaan yang dianggap tidak berdasar dalil yang kuat.
Prinsip Muhammadiyah terangkum dalam pendekatan: Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, Menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan, dan Menolak taqlid buta, namun menghormati ijtihad orang lain
Rasulullah SAW bersabda:
إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ
“Apabila seorang mujtahid berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis Rasulullah SAW di atas mengandung pesan penting tentang sikap Islam terhadap perbedaan pendapat. Hadis ini menegaskan bahwa usaha sungguh-sungguh dalam memahami ajaran Allah melalui ijtihad adalah sesuatu yang mulia dan dihargai, meskipun hasilnya tidak selalu sama atau bahkan bisa keliru.
Kebenaran dalam ijtihad memang diupayakan, tetapi Allah menilai kesungguhan, kejujuran, dan niat mencari kebenaran, bukan semata-mata hasil akhirnya.
Karena itu, perbedaan pandangan yang lahir dari proses ijtihad yang sah tidak boleh disikapi dengan sikap saling menyalahkan, apalagi menyesatkan.
Hadis ini menjadi landasan kuat bahwa ikhtilaf di kalangan ulama dan umat Islam adalah bagian dari dinamika keilmuan yang mendapat legitimasi syariat.
Dalam konteks kehidupan umat Islam hari ini, hadis tersebut mengajarkan kedewasaan beragama: teguh pada keyakinan yang diyakini benar, namun tetap menghormati perbedaan pandangan orang lain sebagai hasil ijtihad yang juga bernilai pahala di sisi Allah.
Perbedaan Jangan Dijadikan Identitas Permusuhan
Sebagai orang Muhammadiyah, penulis berpendapat bahwa kesalahan terbesar umat Islam hari ini adalah mengubah perbedaan fiqh menjadi identitas permusuhan, bukan sebagai khazanah keilmuan.
Ketika perbedaan qunut, tarawih, atau metode hisab-rukyat dijadikan ukuran “paling sunnah” atau “paling benar”, maka agama kehilangan ruhnya sebagai rahmat.
Padahal Rasulullah SAW mengingatkan:
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
“Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi)
Jadi, Akhlak mendahului kemenangan orang saat ber-argumen.
Bagi Muhammadiyah, tajdid bukan berarti memonopoli kebenaran, melainkan menghadirkan Islam yang mencerahkan, rasional, dan membawa kemaslahatan. Karena itu, berdialog dengan NU, Salafi, LDII, dan lainnya bukan ancaman, melainkan kebutuhan umat.
***
Umat Islam tidak harus seragam untuk bersatu. Kita cukup sepakat dalam hal-hal prinsip: tauhid, kenabian, Al-Qur’an, dan akhlak. Adapun perbedaan dalam cabang ibadah dan metode dakwah, biarlah menjadi ladang ijtihad.
Sebagaimana kaidah yang sangat dikenal dalam Muhammadiyah:
نَتَّحِدُ فِي الْعَقِيدَةِ، وَنَتَسَامَحُ فِي الْفُرُوعِ، وَنَتَعَاوَنُ فِي الْمَصَالِحِ
“Kita bersatu dalam akidah, bersikap toleran dalam perkara cabang (furu’iyah), dan saling bekerja sama dalam kemaslahatan,”
Jika prinsip ini dipegang, maka perbedaan tidak akan melemahkan umat, justru memperkaya peradaban Islam di Indonesia; sebuah Islam yang berkemajuan, damai, dan berkeadaban. (*)
وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ













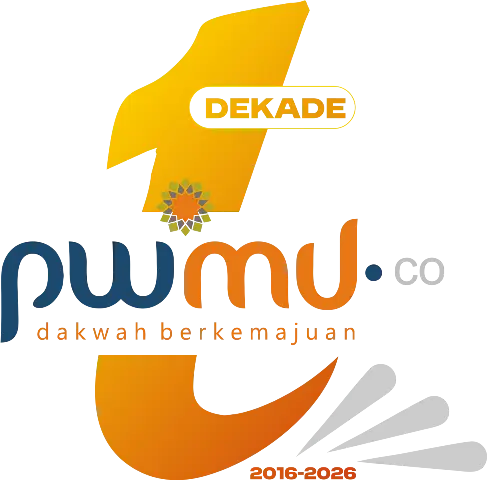

0 Tanggapan
Empty Comments