
Oleh: Ahmad Soleh (Sekretaris MPI PDM Kota Depok, Mahasiswa MPBI SPs Uhamka, dan Anggota APEBSKID Kom. DKI Jakarta)
PWMU.CO- Saat ini, hampir setiap orang menggenggam ponsel pintar. Kecerdasan artifisial (AI) dan media sosial semakin melekat erat dengan kehidupan manusia. Teks, foto, dan video mengalir deras tanpa kita minta atau cari. Ratusan ribu informasi berseliweran melalui perangkat komunikasi kita setiap hari. Adakah orang yang bisa lepas dari gawai barang sehari saja? Rasanya sangat sulit. Takut ketinggalan informasi, takut dianggap kudet alias “kurang up to date”. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan ponsel pintar, agaknya menjadi fakta yang sulit dibantah.
Memang, manusia dan informasi adalah dua sisi mata uang. Sebagai makhluk sosial (Homo socius), manusia membutuhkan interaksi, komunikasi, dan berbaur dengan sesamanya. Aktivitas ini mengharuskan kita saling bertukar sesuatu yang berharga, yang kita sebut “informasi”. Entah dalam bentuk obrolan ringan, diskusi berat, atau sekadar bertukar cerita.
Tanpa informasi, manusia bisa teralienasi dari pergaulan dan kehidupan sosial. Kebutuhan akan informasi inilah yang menuntut kehadiran media yang memudahkan manusia mendapatkan informasi, baik sebagai kebutuhan, gengsi, atau “alat tukar” dalam interaksi sosial. Dalam sudut pandang lain, informasi memiliki andil besar dalam membangun wacana dan percakapan publik.
Saat Semua Merasa Ahli
Di Indonesia, kita mengenal sejumlah media besar, seperti Kompas, Republika, Tempo, dan Jawa Pos, hingga media digital seperti Detik, Kumparan, dan Narasi. Media massa bukan hanya berperan sebagai penjual, tetapi juga sebagai produsen informasi. Media massa adalah produk jurnalistik yang prosesnya terikat oleh prinsip, semangat, dan kode etik yang ketat.
Keterikatan ini menjadi pembeda utama antara media massa dan sumber informasi lainnya. Namun, di era digital ini, media massa menghadapi tantangan besar. Menurut Raman Narayanan, seorang redaktur media the AJC di AS (dikutip Masha, 2020), perubahan ini disebabkan preferensi anak muda yang lebih suka membaca berita lewat internet. Ini adalah masa transisi yang sulit, di mana banyak media harus menyetop produk cetak sebagai produk utama mereka. Namun, tantangan berat justru datang dari demokratisasi informasi.
Demokratisasi informasi dipicu oleh kemunculan internet dan media baru (new media) seperti blog, forum, hingga media sosial. Keberadaan media sosial yang mudah diakses menjadikan semua orang memiliki ruang untuk memproduksi dan membagikan informasi secara luas dan tak terbatas. Seperti yang diungkapkan Walter Lippmann (dalam Ishwara, 2011), di era ini setiap orang bisa menjadi wartawan. Semua orang merasa berhak bersuara dan melontarkan pendapatnya. Semua merasa dirinya ahli yang perlu dan penting untuk didengarkan.
Jika media massa menyaring narasumber berdasarkan keahlian, media sosial sangat demokratis, siapa pun bisa berbicara. Ironisnya, publik kini cenderung lebih percaya pada pendapat orang yang populer di media sosial daripada pendapat ahli. Fenomena ini secara gamblang digambarkan oleh Tom Nichols (2017) sebagai era matinya kepakaran (the death of expertise). Sebuah era di mana publik lebih percaya omong kosong dibandingkan pendapat pakar.
Nichols berpendapat, “Ruang publik semakin didominasi orang kurang informasi, yang sebagian besar belajar sendiri dan memandang rendah pendidikan formal, serta merendahkan pengalaman.” Padahal, kita tahu tidak seorang pun ahli dalam segala hal. Demokratisasi informasi membuat semua orang merasa berhak berpendapat, bahkan banyak yang tersesat dalam anggapan bahwa “pendapat yang paling banyak disetujui warganet adalah pendapat yang benar”. Akibatnya, informasi menjadi bias, liar, dan menyesatkan.
Omong Kosong Terus Diproduksi
Di era digital, media sosial sebagai new media telah mengubah pola informasi di ruang publik. Algoritma dan viralitas menjadikannya memiliki daya ledak luar biasa. Demokratisasi yang seharusnya memberikan kebebasan justru menjebak kita dalam ruang digital yang “dikendalikan” oleh algoritma. Jika percakapan kita diatur oleh mesin, lantas di mana letak demokratisnya?
Aktivitas kita di media sosial mengurung kita dalam ruang sempit yang disesaki informasi berdasarkan preferensi yang diukur oleh algoritma. Inilah yang kita kenal sebagai echo chamber dan filter bubble. Alih-alih mendapatkan informasi yang beragam, kita justru terperangkap dalam satu sudut pandang. Tak heran jika perdebatan di kolom komentar sering kali berakhir sebagai debat kusir, di mana tujuan utamanya adalah membuktikan “akulah yang benar”, bukan mencari kebenaran (truth) itu sendiri.
Inilah gerbang kita memasuki era konten dan omong kosong. Produksi omong kosong di jagat digital kian masif ketika setiap orang merasa bisa menjadi terkenal dalam sekejap. Banyak konten yang viral bukanlah kualitasnya, melainkan konten berisi omong kosong, sensasi, dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan daya literasi yang rendah, masyarakat kita mudah sekali diperdaya dengan konten semacam itu.
Hoaks, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi adalah varian dari omong kosong yang terus diproduksi. Bukan hanya karena ada yang memproduksinya, tetapi juga karena banyak warganet yang gemar mengonsumsinya. Kebiasaan mendapatkan informasi sesuai preferensi dan kesenangan pribadi dapat memperkuat bisnis semacam ini. Kerentanan masyarakat minim literasi terhadap omong kosong semakin besar ketika orang-orang licik menggunakan jasa buzzer untuk menyebarkannya.
Menghadapi Omong Kosong
Memang, sejak lama kita sudah hidup berdampingan dengan omong kosong. Sebagian dari kita bahkan meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah gerbang kita memasuki era post-truth, di mana kebenaran menjadi relatif, bergantung pada kepentingan, preferensi, dan keyakinan. Tidak ada lagi objektivitas. Validasi digunakan untuk pembenaran, sementara verifikasi tidak lagi berjalan semestinya.
Tom Phillips dalam bukunya, Truth (2021), menegaskan bahwa dalam menghadapi omong kosong, kita perlu memeriksa diri sendiri. Apakah ada bias yang memengaruhi cara kita melihat kebenaran? Jujur terhadap diri sendiri terkadang sulit. Kita tidak ingin dibohongi, tetapi pada saat yang sama, kita kerap tertarik membeli barang karena iklan, hingga memilih pejabat politik karena tergiur janji-janji kampanye.
Secara psikologis, kita juga kerap berbohong pada diri sendiri—membuat media sosial menjadi tempat kita membagikan momen yang sudah direkayasa sedemikian rupa, contohnya. Lars Svendsen dalam Filsafat Kebohongan (2025) mengatakan, berbohong membuat seseorang percaya apa yang diucapkannya sebagai kebenaran. Orang yang berbohong akan meyakinkan orang lain untuk percaya dengan kebohongannya. Itulah yang dilakukan pengiklan dan pejabat saat kampanye.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita mau menjadi bagian dari produsen/konsumen omong kosong? Atau, bergerak menghentikan segala omong kosong itu sekarang juga? (*)
Editor Alfain Jalaluddin Ramadlan













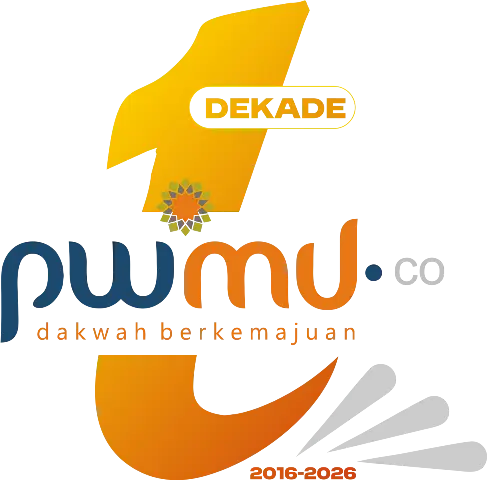

0 Tanggapan
Empty Comments