Sekilas, membandingkan Muhammadiyah dengan Manchester United (MU) tampak seperti sebuah anomali intelektual, yakni sebuah cocoklogi yang dipaksakan antara ormas Islam modernis terbesar di dunia, dengan klub sepak bola paling komersial di Inggris dengan fanbase global.
Namun, jika kita bersedia mengupas lapisan permukaannya, menyingkirkan jubah teologis di satu sisi dan jersey olahraga di sisi lain, kita akan menemukan dua “raksasa peradaban” yang bergerak di atas rel sejarah yang paralel. Keduanya bukan hanya kerumunan massa, mereka institusi yang dibangun di atas etos kemandirian, sistem kaderisasi yang rigid dan kemampuan beradaptasi terhadap zeitgeist (jiwa zaman) tanpa kehilangan identitas puritan mereka.
Banyak yang tidak menyadari bahwa kedua entitas ini lahir dari rahim sosiologis yang nyaris serupa, meski terpisah jarak ribuan kilometer. Manchester United, yang bermula sebagai Newton Heath LYR Football Club pada 1878, didirikan oleh kaum buruh kereta api di tengah kepulan asap hitam Revolusi Industri Inggris.
Mereka adalah representasi kelas pekerja yang mencari harga diri. Tiga dekade kemudian, pada 1912, Muhammadiyah lahir bukan di lingkungan pesantren pedesaan yang aristokratik, melainkan di Kauman: pusat denyut nadi pedagang dan pengusaha batik kota.
Keduanya lahir dari semangat middle-class resilience atau ketahanan kelas menengah-bawah. Jika MU lahir sebagai antitesis terhadap kaku-nya kehidupan industri, Muhammadiyah lahir sebagai respons (tajdid) terhadap kaku-nya pemahaman agama dan penindasan kolonial. Ada semangat self-help yang kental di sana: keyakinan bahwa nasib tidak akan berubah jika hanya menunggu belas kasihan penguasa atau pemilik modal.
Lebih dari ‘Membeli Pemain’
Jika ada satu hal yang membuat kedua institusi ini bertahan lebih dari satu abad, jawabannya bukan pada uang, melainkan pada manusianya.
Dalam dunia sepak bola, Manchester United dikenal dengan filosofi “If they are good enough, they are old enough” (Jika mereka sudah layak secara kemampuan, maka mereka pantas diberi kesempatan).
Sejarah mencatat tinta emas Busby Babes di tahun 50-an hingga Class of ’92 di era Ferguson. MU memiliki DNA untuk tidak hanya membeli bintang instan, tetapi mencetak bintang dari akademi mereka sendiri di Carrington. Mereka percaya pada proses, pada doktrinasi nilai sejak usia dini.
Muhammadiyah pun demikian, bahkan mungkin lebih radikal. Organisasi ini memiliki sistem kaderisasi yang bisa dibilang paling rapi di dunia Islam modern. Muhammadiyah tidak perlu “mengimpor” ketua umum atau tokoh sentral dari luar karena “akademi” mereka: mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), hingga Pemuda Muhammadiyah tidak pernah berhenti “berproduksi”.
Perkaderan Darul Arqam adalah “Carrington”-nya Muhammadiyah, sebuah kawah candradimuka tempat ideologi disuntikkan dan loyalitas dibentuk. Keduanya mengajarkan kita bahwa institusi yang besar tidak dibangun dengan cara instan, melainkan lewat investasi panjang pada sumber daya manusia.
Etalase Manusia Unggul
Bukti paling valid dari keunggulan sebuah sistem bukanlah pada tumpukan dokumen renstra organisasi, melainkan pada kualitas manusia yang dihasilkannya. Di Manchester, dunia pernah terhenyak oleh fenomena Class of ’92. Saat itu, ketika klub-klub lain sibuk memecahkan rekor transfer, MU justru memanen hasil didikan mereka sendiri. Nama-nama seperti David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs hingga Gary Neville tidak hanya pesepak bola dengan teknik tinggi, mereka adalah penjaga nyala api filosofi klub.
Mereka memahami sejarah, merasakan denyut nadi tribun Stretford End, dan bermain dengan kebanggaan yang tidak bisa dibeli dengan gaji mingguan. Bahkan di era modern, muncul sosok Marcus Rashford, binaan asli akademi yang tidak hanya tajam di lapangan, tetapi juga vokal dalam isu sosial, mencerminkan bahwa didikan MU melahirkan karakter, bukan sekadar atlet robotik. Ini adalah warisan panjang yang ditarik sejak era Sir Bobby Charlton dan Duncan Edwards, para “Busby Babes” yang membuktikan bahwa talenta muda, jika diberi kepercayaan, bisa menaklukkan dunia.
Di sisi lain, jika kita menengok ke dalam “rahim” Muhammadiyah, kita akan menemukan deretan nama yang jejaknya melampaui batas organisasi. Kaderisasi Muhammadiyah tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga negarawan dan ksatria. Siapa yang bisa menyangkal peran Jenderal Sudirman? Bapak Tentara Nasional Indonesia ini bukanlah lulusan akademi militer barat, melainkan seorang guru Muhammadiyah dan kader pandu Hizbul Wathan (HW). Disiplin militer dan napas perjuangannya ditempa dalam sistem perkaderan kepanduan Muhammadiyah yang mengajarkan cinta tanah air sebagai bagian dari iman.
Sistem ini juga melahirkan para arsitek bangsa. Ada Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo, tokoh kunci perumus dasar negara yang integritas politiknya terbentuk dari nilai-nilai persyarikatan. Ada Ir. Soekarna, proklamator kemerdekaan dan masih banyak yang lainnya. Di era kontemporer, “akademi” Muhammadiyah melahirkan pemikir bangsa dengan spektrum luas: dari Buya Syafi’i Maarif yang menjadi “guru bangsa” dan kompas moral pluralisme, Amien Rais yang menjadi lokomotif reformasi politik 1998, hingga teknokrat-intelektual seperti Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti yang kini memegang peran strategis di Republik ini.
Sama seperti Beckham dan Scholes yang tidak perlu diajari lagi tentang apa artinya mengenakan seragam “Setan Merah”, tokoh-tokoh seperti Sudirman hingga Buya Syafi’i tidak perlu lagi diragukan komitmennya terhadap republik. Mereka adalah bukti hidup bahwa baik di lapangan hijau Old Trafford maupun di ruang-ruang diskusi Menteng Raya, sebuah sistem kaderisasi yang unggul akan selalu melahirkan protagonis zaman yang mengubah sejarah.
Namun, romantisme sejarah dan kaderisasi saja tidak cukup untuk menghidupi organisasi raksasa; di sinilah letak kejeniusan manajerial keduanya. Muhammadiyah sering dijuluki sebagai “State within a State” atau Negara di dalam Negara.
Bukan karena ambisi politik, melainkan karena kemandirian finansialnya yang mencengangkan. Melalui teologi Al-Ma’un, Muhammadiyah menerjemahkan kesalehan menjadi aset produktif. Ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, hingga perguruan tinggi adalah “mesin ekonomi” yang membuat Muhammadiyah bisa tetap tegak kepala di hadapan kekuasaan. Mereka mempraktikkan social entrepreneurship jauh sebelum istilah itu menjadi tren di sekolah bisnis Harvard.
Paralel dengan itu, Manchester United adalah pionir dalam industri sepak bola modern yang mengubah klub menjadi korporasi global yang mandiri. Sebelum era “klub negara” yang didanai minyak (seperti Manchester City atau PSG), MU membangun kejayaannya dari monetisasi brand, penjualan tiket, dan merchandise. Keduanya memegang teguh prinsip sakral: kedaulatan ideologi hanya bisa dicapai jika ada kedaulatan ekonomi. Muhammadiyah tidak perlu menjadi “peminta-minta” proposal ke pemerintah untuk menjalankan misinya, sebagaimana MU (secara historis) tidak menggantungkan nasib pada suntikan dana eksternal untuk membeli pemain.
Tentu, jalan sejarah tidak selalu mulus. Manchester United pernah hancur lebur dalam Tragedi Munich 1958, dan Muhammadiyah pernah menghadapi tekanan politik luar biasa di berbagai rezim. Namun, kemampuan mereka untuk bangkit (bounce back) membuktikan bahwa mereka bukan organisasi yang bergantung pada satu figur.
Meski hari ini fans MU mungkin merindukan sosok Ferguson, dan warga Muhammadiyah merindukan figur masa lalu, sistem yang telah dibangun membuat kapal besar ini tidak karam.
Muhammadiyah tidak bubar sepeninggal Ahmad Dahlan, dan MU tetap menjadi klub dengan valuasi tertinggi meski prestasi sedang naik turun.
Pada akhirnya, kesamaan prinsip antara Sang Surya dan Setan Merah mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal: bahwa gerakan yang abadi adalah gerakan yang melembaga. Menjadi “warga Muhammadiyah” atau menjadi “Mancunian” bukan lagi sekadar pilihan rasional, melainkan sebuah identitas. Di tengah dunia yang serba instan ini, keduanya berdiri sebagai monumen yang mengingatkan bahwa ketekunan mengelola sistem, kemandirian ekonomi, dan kesetiaan merawat kader adalah kunci untuk memenangkan pertarungan melawan waktu.













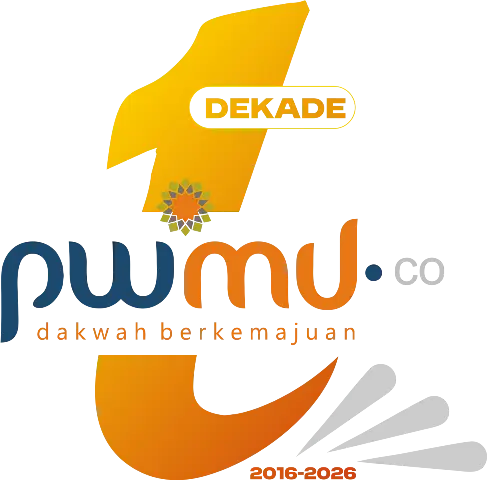

0 Tanggapan
Empty Comments