Desa Godog, Kecamatan Laren, tenggelam dalam hening yang dalam pada malam Selasa, 18 November 2025. Tepat di hari Milad Muhammadiyah ke-113, kabar duka itu datang; pelan, namun memukul semua rasa: Pendekar Besar Tapak Suci, KH Ahmad Kasuwi Thorif, MA., P.Br, atau yang selama puluhan tahun disapa semua muridnya sebagai Abah Wi, berpulang ke rahmatullah.
Kabar itu menyambar cepat. Dalam hitungan menit, pesan-pesan duka berloncatan di berbagai grup, dan dalam hitungan jam, ribuan kaki melangkah menuju Godog. Mereka datang dari Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Pacitan, bahkan Malaysia. Murid, sahabat, warga, pendekar, aktivis Muhammadiyah semua berduyun-duyun.
Rabu pagi, Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Godog penuh sesak. Dari halaman, serambi, hingga jalan kampung, jamaah berdiri rapat. Jenazah dishalatkan tiga gelombang, pukul 09.00 WIB, sebagai tanda betapa luas cintanya umat kepada beliau.
Dan ketika jenazah dibawa menuju makam, warna merah Tapak Suci mengalir seperti sungai panjang: tanda hormat terakhir untuk sang guru yang telah mencetak ribuan kader silat dan kader dakwah.
Namun kisah tentang Abah Wi bukan berhenti pada momen duka. Ia hidup di dada murid-muridnya yang kini memberikan kesaksian kepada PWMU.CO.
Pendekar Khoirul Muslimin
Ketua PIMDA 026 Tapak Suci Lamongan, Khoirul Muslimin, membuka kisahnya dengan suara bergetar ketika dihubungi PWMU.CO.
“Yang Abah ajarkan kepada saya sama dengan yang diajarkan kepada pendekar lain,” ujarnya. “Jurus nasional, Kanjeng Sepuh, Sedayuan. Semua ilmu Tapak Suci yang sudah ditetapkan pimpinan pusat. Tidak pernah keluar dari itu.”
Namun, yang paling terpatri dalam dirinya bukan sekadar jurus.
“Abah itu gemati. Ngemong sampai ke hal-hal kecil. Padahal jujur, kadang saya ini murid yang membosankan. Tapi beliau tidak pernah berhenti mengarahkan agar saya sabar. Itulah yang saya ingat.”
Ada satu peristiwa yang tak dilupakannya. “Pernah saya marah besar, tidak bisa mengontrol emosi,” kenangnya.
“Lalu Abah mengajak saya sholat. Habis sholat, Abah duduk di depan saya, membuka Al-Qur’an, dan menunjuk satu ayat. ‘Baca,’ katanya.”
Ayat itu menjadi penuntun hidupnya sampai kini, bahkan ia ajarkan kepada murid-muridnya.
“Semoga saya tidak lupa apa yang Abah ajarkan. Itu semua saya wariskan supaya ilmu Abah tidak padam.”

Alimah: Anak Perempuan Pertama di Tapak Suci Lamongan
Air mata Alimah jatuh bahkan sebelum ia mulai bercerita.
“Abah Wi bagi saya itu orang tua. Saya ini anak perempuan pertama yang beliau terima di Tapak Suci Lamongan. Dari kecil, saya dibonceng ke mana-mana saat beliau mengembangkan Tapak Suci.”
Pendidikannya keras. “Tapi berkat itu, saya bisa setegar sekarang.“
Alimah berhenti lama ketika menceritakan penyesalannya.
“Abah… maafkan aku. Aku lama tidak berkunjung. Aku ini anak yang suka protes, cerewet, kadang menyakiti hati. Tapi Abah tetap sayang. Aku tidak sempat minta maaf sebelum Abah pergi.”
Ada satu momen yang membuatnya menahan napas lama:
“Waktu wisuda S1 tahun 2002 di Paciran, Abah tahu namaku dipanggil. Beliau langsung ke pintu belakang, menunggu aku keluar. Hanya ingin memastikan aku hadir dan bilang, ‘Selamat ya, Nduk.’ Lalu beliau memelukku…”
Ia menangis pelan. “Itu pelukan orang tua. Aku anaknya. Dan Abah benar-benar menyayangiku.”

Beny Febriyanto: “Aku Tumbuh Bersama Abah Wi
Bagi Beny Febriyanto, Abah Wi bukan sekadar guru silat. Bukan pula sekadar tokoh Muhammadiyah yang dihormati.
“Beliau itu seperti ayah kedua saya, tempat saya pulang, tempat saya belajar hidup,” katanya pelan, seolah memilih kata dari ruang kenangan yang jauh.
Dari Anak Kelas X MA yang Gugup, Menjadi Murid Kepercayaan
Tahun 2010, Beny masih siswa kelas X MA. Tubuhnya ringkih, geraknya kaku. Ketika pertama kali datang ke halaman rumah Abah Wi di Godog, ia mengaku gemetar.
“Abah memandang saya dengan sorot mata yang tegas, tapi hangat. Lalu beliau bertanya, ‘Kowe siap sinau tenanan, Le?’”
Dan Beny hanya bisa mengangguk.
Hari pertama, ia tidak langsung diajari jurus.
Abah mengajarinya Doa Pembukaan dan Ikrar Tapak Suci.
“Beliau bilang, ‘Iki pondasemu. Jurus tanpa iman, gak ana gunane.’”
Itulah pelajaran pertama: Tauhid sebelum teknik. Adab sebelum tenaga.
Sejak hari itu, Beny tidak pernah absen. Tidak peduli hujan, dingin, atau sedang tidak enak badan, ia tetap datang. Dan Abah selalu memperhatikan—meski tidak mengucapkan apa-apa.
Dari Belajar Silat, Menjadi Teman Perjalanan
Kedekatan itu makin kuat. Abah mulai mengajak Beny pergi ke berbagai tempat.
Kadang hanya ke sawah, kadang ke tempat sunyi di pinggir desa, kadang ke hutan kecil tempat Abah mencari burung.
“Tapi sambil mencari burung itu, Abah berceramah tentang hidup. Tentang sabar, tentang berdakwah, tentang memimpin.”
Tidak ada yang tahu betapa seringnya Abah melakukan perjalanan berdua dengan Beny.
Kadang mereka pergi sore-sore lalu pulang malam. Kadang hanya untuk melihat murid latihan. Kadang hanya untuk mampir ke rumah warga.
“Yang membuat saya terkesan, Abah itu suka mendengarkan. Beliau mau mendengar curhatan murid kecil seperti saya. Tapi setelah itu beliau memberi nasihat yang rasanya menempel di kepala sampai hari ini.”
Mendirikan Tapak Suci Lembung (2011): Tugas Pertama yang Berat
Tahun 2011, Abah mengajak Beny ke Desa Lembung, Kalitengah.
“Le, aku butuh awakmu,” katanya singkat.
Mereka membuka latihan pertama. Pesertanya puluhan: bapak-bapak, pemuda desa, bahkan anak-anak.
Abah memimpin latihan pembukaan. Suaranya lantang, geraknya tegas.
Setelah itu, Abah memanggil Beny ke samping.
“Le… mulai besok, sampean yang neruske. Aku percaya.”
Beny terdiam. Ia belum 17 tahun.
“Itu pertama kalinya Abah memberikan amanah besar. Dan amanah itu mengubah hidup saya.”
Ia pulang ke Godog dengan perasaan campur aduk: bangga, takut, tapi juga merasa dihargai.
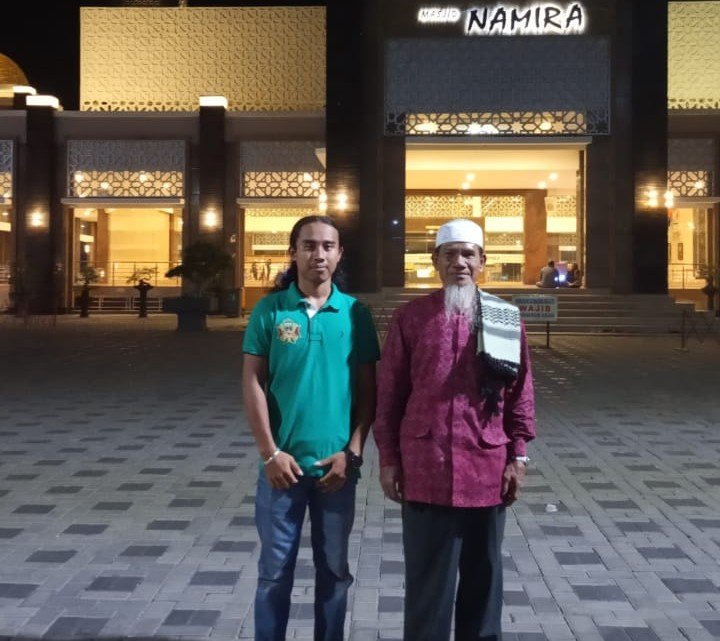
Perjalanan Panjang: Menemani Abah ke Banyak Daerah
Tahun-tahun berikutnya, nama Beny seakan tidak pernah lepas dari Abah Wi. Keduanya sering terlihat bersama.
Godog–Pacitan: Perjalanan 8 Jam yang Tidak Pernah Ia Lupa. Untuk menghadiri Musyda, Abah mengajak Beny mendampingi.
Mereka berangkat subuh, melewati pegunungan, jalan sempit, dan daerah hening yang jarang dilewati kendaraan.
“Di tengah perjalanan, Abah cerita tentang masa mudanya, bagaimana ia pertama kali belajar silat, bagaimana dirikannya Tapak Suci di berbagai tempat. Itu rasanya seperti mendengarkan sejarah hidup yang belum pernah ditulis.”
Kemudian diajak mengikuti Jambore Nasional di Sleman (2016) ketika Abah Wi menjadi pemateri.
Beny bertugas menyiapkan seluruh keperluan Abah: pakaian, perlengkapan, sampai materi presentasi.
“Itu pertama kalinya saya melihat Abah berdiri di depan ratusan kader dari seluruh Indonesia. Saya bangga sekali…”
Selain itu diajak Rapat Pimwil II Tapak Suci Jawa Timur. Meski usia Abah sudah senja, semangatnya seperti anak muda.
“Kadang saya yang kalah capek,” Beny tertawa kecil.
Abah tidak pernah mengeluh. Tidak pernah minta diperlakukan istimewa.
Kemudian diajak Takziyah dan Silaturahim ke para Pendekar.
Abah sering datang ke rumah Pendekar dan warga yang bahkan tidak begitu ia kenal.
“Kalau ada yang sakit, Abah datang. Kalau ada yang meninggal, Abah datang. Itu dakwahnya.”
Dan Beny selalu ikut.
Tiga Tahun Terakhir: Titipan Ilmu yang Paling Rahasia
Dari ratusan murid, Abah memilih beberapa orang saja untuk diberi ilmu khusus: meliwis, Kanjeng Sepuh, dan jurus-jurus tinggi lainnya.
Setiap pekan, ia memanggil Beny, Anas, Pudin, Udin, Bayu, dan Jauhari.
Mereka berkumpul di rumah Abah. Suasana hening.
“Atine kudu resik,” kata Abah.
“Yang paling saya tidak lupa adalah: Abah menyentuh bahu saya dan berkata, ‘Iki kanggo awakmu, Le. Dunia ora usah ngerti. Sing penting manfaat.’”
Beny terdiam lama ketika menceritakan bagian ini.

Kenangan Terakhir: Perjalanan ke Payaman
Sekitar sebulan sebelum wafat, Abah menelpon Beny.
“Le, ayo antarno aku tuku mangan.”
Mereka berangkat berdua, seperti dulu-dulu.
Abah duduk di belakang motor, memegang pinggang Beny seperti seorang ayah yang mempercayai anaknya.
“Di situ saya tidak tahu bahwa itu perjalanan terakhir saya bersama Abah…”
Sepanjang jalan, Abah bercerita tentang masa tua. Tentang perjuangan. Tentang Tapak Suci. Tentang harapan-harapannya.
“Yang saya ingat, Abah bilang:
‘Le, nek aku wes ora onok… terusno dakwah iki. Jawabane nang Gusti Allah.’”
Itu kalimat yang, setelah wafatnya, terus terngiang di telinga Beny.
Saat Abah Pergi…
Ketika kabar itu datang, Beny merasa lututnya lemas.
“Rasane kaya separo jiwa saya ilang…”
Ia datang ke rumah duka paling awal.
Ia memeluk jenazah Abah lama.
Ia menangis tanpa suara.
“Saya kehilangan guru, kehilangan ayah, kehilangan cahaya. Tapi saya juga menemukan amanah yang harus saya jaga sampai mati.”
Nur Arif Syaifudin: Guru yang Sangat Keras Dulu, Sangat Lembut di Usia Senja”
Nur Arif Syaifudin menggambarkan Abah dengan empat kata: penyayang, pejuang, mengagumkan, dan menyenangkan.
“Rumah Abah itu rumah kami. Mau makan, minum, istirahat dipersilakan.”
Ia terkesan dengan kegigihan Abah.
“Umurnya sudah 72 tahun, tapi masih mau mengajari kami, anak-anak muda yang tidak ada apa-apanya.”
Terkait gaya mengajar, Udin membandingkan masa muda dan masa tua Abah Wi.
“Dulu keras sekali. Sampai gedek rumahnya pernah jebol karena murid terlempar saat latihan.”
“Sekarang, beliau sangat lembut. Ngemong. Kalau ada yang tidak hafal jurus, beliau sabar menunggu.”
Dan yang membuatnya tak bisa lupa adalah nasihat pendek yang menohok:
“Semua orang pasti sibuk. Yang tidak mau sibuk, mati saja.”
Nasihat itu diberikan ketika ada murid yang enggan diajak berjihad dengan alasan sibuk.

Asrufin Ramadhani: AbahWi Lebih dari Guru, Beliau Itu Bapak Saya
Asrufin bicara pelan, seperti memilih kata dengan sangat hati-hati.
“Sebagai murid, saya menilai Abah itu lebih dari guru. Saya ngaji ke beliau, silat ke beliau, hidup saya banyak dibimbing oleh beliau.”
Ia belum siap ditinggal. “Saya masih butuh belajar banyak. Beliau sumber keilmuan. Kehilangan ini terlalu dalam.”
Abah bahkan menitipkan pesan penting kepadanya:
“Tolong bimbing cucuku. Aku ingin cucuku jadi atlet berprestasi.”
Dan satu pesan lagi yang selalu berulang:
“Kembangkan Tapak Suci di Laren dan Lamongan. Jangan berhenti.”
Akhirnya… Warisan Itu Ada pada Murid-Muridnya
Kini Abah Wi telah pergi. Tapi ajarannya berputar di dada murid-muridnya.
Mereka masih mendengar sorban putih itu berkibar.
Masih melihat jenggot putihnya yang khas.
Masih mendengar suaranya memanggil: “Nduk… Le… ayo latihan.”
Dan mungkin, di antara desir angin Desa Godog yang hari ini terasa lebih sunyi dari biasanya, ada satu pesan Abah yang kembali terucap dari hati seorang murid:
“Jika kamu cinta Muhammadiyah, cintailah perjuangannya. Jangan berhenti berjihad.”
Selamat jalan, Abah Wi.
Guru para pendekar.
Pendekar para guru.
Cahaya yang tidak padam di Godog, di Lamongan, dan di mana pun ilmu Tapak Suci diajarkan. (*)













0 Tanggapan
Empty Comments