Puasa Ramadan sering dimaknai sebagai latihan menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Namun dalam tradisi etika Islam, puasa jauh melampaui urusan biologis. Ia adalah latihan pengendalian diri secara total: lisan, emosi, pikiran, dan perilaku sosial.
Karena itu, Rasulullah saw memberikan peringatan keras bahwa puasa bisa kehilangan nilainya jika seseorang tidak meninggalkan qawla zūr, perkataan dusta dan perilaku menyimpang.
Masalahnya, di era media sosial, qawla zūr tidak lagi berdiri sendiri sebagai kebohongan individual. Ia menjelma menjadi fitnah kolektif, diproduksi dan disebarkan secara berjamaah melalui scrolling tanpa kendali di gawai.
Di sinilah puasa Ramadan menghadapi ujian paling serius.
Scrolling tampak sebagai aktivitas netral: mengisi waktu, mencari hiburan, atau sekadar mengikuti kabar. Namun dalam kenyataannya, media sosial bukan ruang kosong. Ia adalah arena produksi makna, emosi, dan opini.
Algoritma bekerja dengan logika keterlibatan, bukan kebenaran. Konten yang memancing kemarahan, kecurigaan, dan kebencian justru mendapat panggung lebih besar. Dalam situasi ini, satu sentuhan jari bisa berubah menjadi alat penyebar qawla zūr.
Fitnah hari ini jarang datang dalam bentuk kebohongan telanjang. Ia tampil rapi: potongan video tanpa konteks, kutipan setengah benar, judul provokatif, atau narasi insinuatif yang menggiring emosi.
Banyak orang tidak memproduksi kebohongan, tetapi ikut menyebarkannya. Padahal dalam etika Islam, keterlibatan dalam penyebaran dusta—meski tanpa niat jahat—tetap merupakan dosa moral.
Ironisnya, semua itu sering terjadi saat seseorang sedang berpuasa.
Hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa Allah “tidak membutuhkan” puasa orang yang masih melakukan qawla zūr adalah kritik keras terhadap ritualisme kosong.
Puasa tetap sah secara hukum, tetapi gugur nilainya sebagai sarana pembentukan takwa. Perut kosong, tetapi jempol sibuk menyebarkan prasangka.
Lebih problematis lagi, qawla zūr digital sering berlangsung secara berjamaah. Satu unggahan memicu ribuan komentar, satu narasi memicu gelombang hujatan.
Dalam psikologi sosial, kondisi ini dikenal sebagai moral crowding: individu kehilangan kehati-hatian moral karena merasa larut dalam arus kolektif.
Di media sosial, orang berkata lebih kasar, menuduh lebih mudah, dan menghakimi lebih cepat dibandingkan dalam interaksi langsung.
Puasa, yang seharusnya menumbuhkan kesabaran dan empati, justru dikalahkan oleh adrenalin digital.
Aspek lain yang jarang disadari adalah bagaimana scrolling memproduksi rasa “benar sendiri”. Timeline yang dikurasi algoritma mempersempit sudut pandang, menciptakan ruang gema (echo chamber). Orang hanya melihat konten yang menguatkan prasangka awalnya.
Dalam situasi seperti itu, fitnah tidak lagi dirasakan sebagai fitnah, melainkan sebagai “kebenaran versi kami”. Ketika prasangka kolektif ini diproduksi dan dibagikan sambil berpuasa, puasa kehilangan fungsi etikanya sebagai penjinak ego.
Padahal Nabi Muhammad saw mengajarkan bahwa puasa adalah momen menahan diri dari konflik.
Jika dicaci atau diprovokasi, seorang yang berpuasa dianjurkan mengatakan, “Aku sedang berpuasa.” Kalimat ini bukan sekadar penolakan verbal, tetapi simbol kesadaran moral: tidak semua respons perlu dikeluarkan, tidak semua emosi perlu dituruti.
Media sosial bekerja sebaliknya. Ia mendorong reaksi instan, komentar cepat, dan keberanian berkata apa saja tanpa jeda refleksi.
Dalam konteks tersebut, puasa Ramadan seharusnya menjadi latihan melawan impuls digital, bukan justru dikalahkan olehnya.
Di sinilah urgensi puasa digital sebagai kesadaran etis. Puasa digital bukan gerakan anti-gawai, melainkan praktik pengendalian diri: menahan jari dari ikut menyebarkan kabar yang belum jelas, menahan diri dari komentar yang hanya memperkeruh suasana, dan berani berhenti scrolling ketika emosi mulai terprovokasi.
Sebagaimana puasa melatih imsak dari yang halal demi tujuan yang lebih tinggi, puasa digital melatih penahanan diri dari konten yang “boleh” tetapi merusak jiwa.
Ramadan seharusnya menjadi bulan penyucian, bukan hanya dari makanan, tetapi dari fitnah. Jika puasa gagal menghentikan qawla zūr di ujung jari, maka yang terjadi hanyalah paradoks spiritual: ibadah meningkat, tetapi akhlak digital memburuk.
Di zaman layar, mungkin makna terdalam puasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan menyelamatkan kebenaran dari keramaian fitnah—dimulai dari satu keputusan sederhana: berhenti scrolling, dan menahan jari. (*)













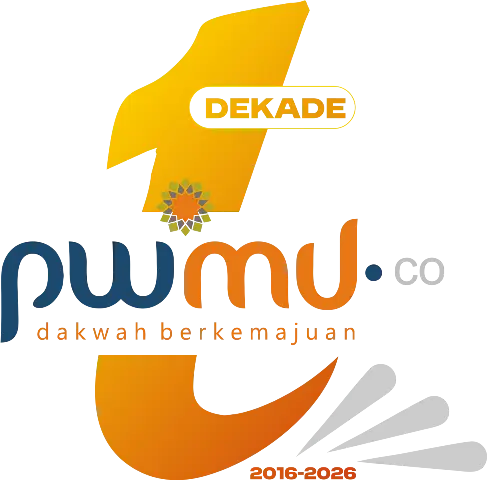

0 Tanggapan
Empty Comments