Di antara hikmah terbesar puasa adalah menghidupkan empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Puasa mengajarkan rasa saat lapar dan haus, kita merasakan sendiri bagaimana sulitnya hidup dalam kekurangan.
Yang biasanya hanya kita dengar, kini kita alami. Dari sinilah empati lahir. Bukan dari kata-kata, tetapi dari rasa.
Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Bukhari dalam Adab al-Mufrad)
Puasa menyadarkan kita bahwa nikmat yang sering kita anggap biasa, ternyata luar biasa bagi orang lain.
Bayangkan seorang ayah yang setiap hari bisa makan tiga kali tanpa berpikir panjang. Ketika ramadan tiba, baru pukul sepuluh pagi perutnya mulai terasa perih. Ia masih bisa bekerja di ruangan ber-AC, masih bisa menahan hingga azan magrib.
Namun di luar sana, ada buruh harian yang tetap memanggul beban berat di bawah terik matahari, ada tukang becak yang mengayuh sejak subuh, ada ibu rumah tangga yang harus menanak nasi untuk anak-anaknya meski dirinya belum tentu ikut makan.
Puasa membuat kita sejenak berdiri di posisi mereka—meski hanya beberapa jam, meski hanya sebagian kecil dari rasa yang mereka tanggung setiap hari.
Atau seorang ibu yang biasa menyiapkan aneka hidangan berbuka. Ketika ia menahan diri seharian, lalu melihat meja penuh makanan, ia tersentak: “Begitu banyak yang Allah titipkan.”
Di saat yang sama, mungkin ada keluarga lain yang berbuka hanya dengan air putih dan sepotong gorengan. Rasa lapar hari itu menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia—dunia kecukupan dan dunia kekurangan.
Empati yang hidup tidak berhenti di perasaan, tetapi berlanjut menjadi tindakan:
- Lebih ringan tangan untuk bersedekah
- Lebih peduli pada fakir, yatim, dan dhuafa
- Lebih berhati-hati agar tidak menyakiti dengan ucapan dan sikap
Allah Ta’ala berfirman: “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma’un: 1–3)
Puasa mengubah cara pandang. Ketika melihat pengemis di lampu merah, hati tidak lagi mudah menghakimi.
Ketika mendengar cerita tetangga yang kesulitan membayar sekolah anaknya, kita tidak lagi sekadar berkata “semoga sabar,” tetapi tergerak mencari jalan membantu.
Di kantor, puasa mengajarkan kita menahan amarah. Saat emosi memuncak karena pekerjaan menumpuk, kita ingat bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga menahan lisan dan sikap.
Di rumah, puasa melatih kita lebih lembut pada pasangan dan anak-anak. Bukankah sering kali yang melukai bukan tangan, tetapi kata-kata?
Puasa melatih kita peka terhadap penderitaan orang lain, peka terhadap kata-kata yang melukai, dan peka terhadap ketidakadilan di sekitar kita
Sensitivitas ini menjadikan seorang mukmin tidak hanya sibuk dengan ibadah ritual, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial. Ia tidak nyaman melihat ketimpangan, tidak tenang ketika ada yang terabaikan.
Orang yang berpuasa sejatinya bukan hanya saleh secara pribadi, tetapi juga peduli secara sosial. Kesalehan tidak berhenti di sajadah, melainkan berlanjut di pasar, di kantor, di sekolah, dan di tengah masyarakat.
Mari jadikan puasa sebagai jalan untuk menghidupkan empati, agar kita tidak hanya kuat menahan lapar, tetapi juga kuat untuk berbagi dan peduli.
Semoga seusai ramadan, empati itu tetap hidup dalam keseharian kita: di rumah, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Bukan hanya sebulan, tetapi sepanjang tahun. Aamiin. (*)













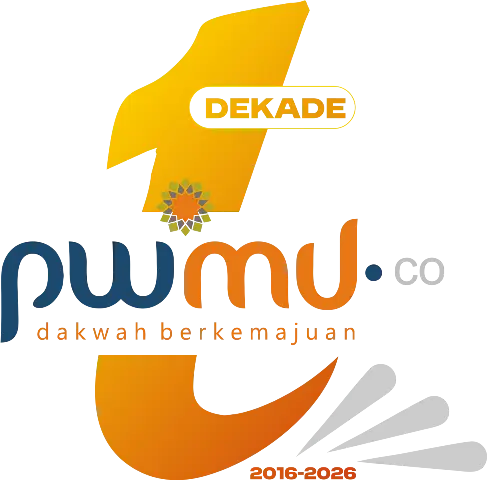

0 Tanggapan
Empty Comments