
PWMU.CO – Saat politik identitas dan polarisasi sosial yang menggerus kohesi kebangsaan menyeruak, Ilmu Kalam — yang sering dianggap sebagai diskusi teologis usang — justru menawarkan kerangka berpikir kritis yang relevan untuk merajut kembali Indonesia yang mulai tercabik. Selama ini, ilmu kalam terkurung dalam pesantren dan perguruan tinggi Islam. Seolah ia hanya milik para teolog yang berdebat tentang takdir atau sifat Tuhan.
Padahal, dalam konteks kebangsaan yang plural seperti Indonesia, ilmu kalam bisa menjadi ‘pisau’ untuk membedah penyakit sosial kita yang antara lain: intoleransi, absolutisme kebenaran, dan kegagapan merespons modernitas.
Pertama, ilmu kalam mengajarkan seni berdebat dengan metodologi yang rigid (adalat al-shara’it). Dalam kehidupan berbangsa, kita kehilangan budaya diskusi yang sehat. Perbedaan pendapat sering berujung pada stigmatisasi — misalnya, label “anti-Pancasila” atau “radikal” yang dilempar begitu saja tanpa argumentasi sistematis. Aliran Mu’tazilah, misalnya, menekankan pentingnya akal dalam memahami teks agama. Prinsip ini bisa menjadi tameng melawan narasi-narasi dogmatis yang kerap dipolitisasi untuk memecah belah. Bayangkan jika elite politik dan warganet mengadopsi etika debat ala ilmu kalam dengan catatan tidak boleh ada yang mengklaim kebenaran mutlak sebelum melalui dialektika yang ketat.
Kedua, ilmu kalam adalah masterclass dalam mengelola kontradiksi. Perdebatan antara Asy’ariyah dan Qadariyah tentang free will melawan determinism, misalnya, mencerminkan dinamika yang juga terjadi dalam demokrasi. Sejauh mana manusia memiliki kebebasan bertindak di bawah “takdir” sistem politik yang kadang korup? Dalam konteks kebangsaan, pertanyaan serupa muncul: “apakah kita benar-benar merdeka menentukan nasib bangsa, atau hanya wayang dalam panggung oligarki?”
Ilmu kalam mengajarkan bahwa jawabannya tidak pernah hitam-putih — sesuatu yang perlu dipahami oleh generasi muda yang kerap terjebak dalam dikotomi “kita versus mereka”.
Yang paling krusial, ilmu kalam sebenarnya adalah ilmu tentang moderasi (wasathiyyah). Konsep irja’ (penundaan penghakiman) yang seperti Murji’ah, misalnya, bisa menjadi antidot terhadap fenomena main hakim sendiri di media sosial. Dalam negara hukum, prinsip “presumption of innocence” sejalan dengan ini. Tak boleh memvonis seseorang hanya berdasarkan asumsi atau prasangka.
“Sayangnya, kita hidup di era ketika vonis agama dan vonis hukum sering kali campuraduk. Ilmu kalam mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang mengetahui isi hati manusia — sebuah pelajaran penting yang kerap hilang di tengah euforia mengkafirkan kelompok lain.”
Namun, upaya menghidupkan ilmu kalam dalam ruang publik tidak bisa setengah hati. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana “menerjemahkan” bahasa teologi yang abstrak menjadi nilai-nilai praktis yang masyarakat awam mudah mencernanya. Di sinilah peran strategis para cendekiawan muslim dan lembaga pendidikan Islam untuk melakukan desakralisasi tanpa desakralisasi. Maksudnya, membuat ilmu kalam tetap sakral secara substansi tapi mudah diakses secara metodologi.
Kita membutuhkan lebih banyak forum diskusi yang mengaitkan konsep-konsep kalam klasik dengan isu aktual, misalnya: bagaimana doktrin qadha dan qadar bisa membantu masyarakat menerima ketidakpastian di tengah krisis ekonomi? Atau bagaimana konsep keadilan Ilahi dalam pemikiran Al-Ghazali bisa menjadi kerangka mengkritik ketimpangan sosial?
Tak kalah penting, ilmu kalam harus keluar dari menara gading akademis dan menyentuh realitas grassroot. Masjid-masjid, pesantren, bahkan ruang digital harus bisa menjadi medan dialektika baru. Bayangkan jika setiap kali ada konflik sosial, para da’i tidak hanya mahir mengutip ayat tentang perdamaian. Da’i juga perlu membekali jamaah dengan kerangka teologis yang mendalam tentang hakikat persatuan dalam perbedaan. Seperti yang dilakukan para ahli kalam terdahulu ketika mereka merumuskan konsep ukhuwah berdasarkan prinsip tauhid.
Atau ketika menghadapi masalah kebangsaan, kita tidak terjebak pada retorika emotif. Kita perlu mampu menganalisisnya melalui lensa maqashid syariah yang telah dikembangkan pemikir kalam kontemporer.
Di sisi lain, kita juga perlu waspada terjadinya reduksi ilmu kalam untuk sekadar menjadi alat legitimasi politik. Sejarah membuktikan bahwa ketika teologi menjadi budak kekuasaan, ia akan kehilangan ruh kritisnya. Karena itu, etika keilmuan dalam tradisi kalam—seperti sikap rendah hati terhadap kebenaran (tawadhu’ ilmi) dan kesediaan untuk terus merevisi pendapat (revised opinion)—harus menjadi panduan utama.
Dalam konteks Indonesia, ilmu kalam harus tetap independen, tidak menjadi corong penguasa maupun oposisi. Harus menjadi suara yang mengingatkan semua pihak tentang prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan universal
Akhir kata, reaktualisasi ilmu kalam bukanlah proyek nostalgia, melainkan gerakan progresif. Ia adalah upaya menghubungkan kembali benang merah antara khazanah intelektual Islam klasik dengan tantangan zaman now. Jika berhasil, ilmu kalam tidak hanya akan menjadi solusi bagi krisis kebangsaan, tetapi juga bisa menempatkan Indonesia sebagai pelopor baru dalam wacana teologi global. Bukan teologi yang hanya membincang surga dan neraka. Teologi juga harus tentang keadilan sosial, toleransi aktif, dan kehidupan berbangsa yang bermartabat. Pada titik inilah ilmu kalam membuktikan diri bukan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai mercusuar peradaban masa depan.***
Editor Notonegoro













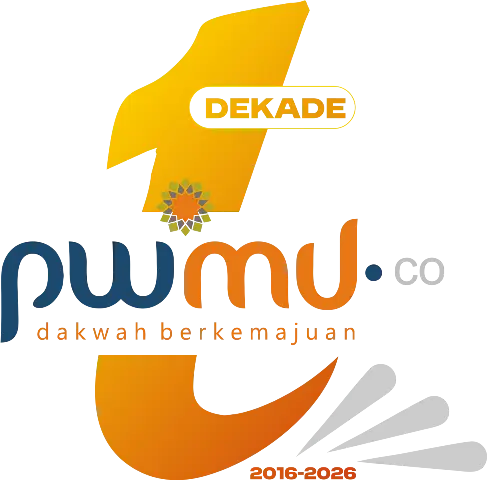

0 Tanggapan
Empty Comments