Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi wajah baru kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Targetnya sangat ambisius: menyediakan asupan nutrisi bagi jutaan siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Namun, di balik visi besar untuk menciptakan “Generasi Emas 2045“, program ini membawa beban fiskal yang sangat besar.
Dengan estimasi anggaran mencapai Rp21 triliun per bulan, muncul perdebatan mengenai prioritas alokasi dana negara.
Beberapa pengamat mengilustrasikan bahwa jika angka fantastis tersebut dialokasikan secara berbeda, Indonesia secara teori mampu membiayai program kuliah gratis bagi seluruh mahasiswa selama 40 tahun ke depan.
Tingginya biaya ini tentu berbenturan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Pembukaan UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Lebih spesifik lagi, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
Pertanyaannya kemudian, apakah pemenuhan “gizi” melalui program MBG merupakan cara paling efektif untuk mencerdaskan bangsa, ataukah alokasi tersebut justru lebih mendesak untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang masih timpang di berbagai pelosok daerah?
Realitas di lapangan menambah keraguan publik.
Belum genap setahun berjalan, program MBG sudah panen persoalan teknis dan manajemen yang serius.
Isu higienitas menjadi rapor merah pertama.
Laporan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi serta tidak higienis banyak beredar di platform media sosial, menunjukkan lemahnya pengawasan pada rantai pasok makanan.
Puncaknya, sejumlah insiden keracunan massal menimpa siswa di berbagai daerah setelah menyantap paket MBG.
Kasus ini bukan sekadar gangguan kesehatan ringan; di Kabupaten Kudus, misalnya, Kepala Dinas Kesehatan Abdul Hakam mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Semarang, sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari 01 terbukti terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli).
Menariknya, tantangan dalam implementasi program makan gratis di sekolah bukan hanya monopoli Indonesia.
Kasus serupa pernah terjadi di Provinsi Gansu, Tiongkok.
Sebanyak 247 siswa taman kanak-kanak mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan gratis di sekolah.
Investigasi otoritas Tiongkok mengungkap fakta mengerikan: makanan tersebut mengandung pewarna bubuk industri berbahaya yang dibeli secara daring.
Pewarna ilegal itu sengaja digunakan untuk membuat tampilan makanan lebih menarik bagi anak-anak, meskipun jelas tertulis bahwa zat tersebut bukan untuk konsumsi manusia.
Hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan timbal melebihi 20%—sebuah angka yang sangat berisiko bagi perkembangan anak.
Respon pemerintah Tiongkok sangat tegas; enam orang ditangkap secara kriminal, sementara 30 pejabat dan staf terkait diperiksa atas dugaan kelalaian.
Pemerintah setempat bahkan menanggung seluruh biaya perawatan medis hingga ke luar daerah bagi para korban.
Berbeda dengan Tiongkok, respons pemerintah Indonesia terhadap kasus keracunan justru memicu polemik baru.
Berdasarkan data, tercatat sekitar 28.000 penerima manfaat (dari laporan lain menyebutkan angka ribuan siswa di berbagai daerah) mengalami gangguan kesehatan akibat program ini.
Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang dinilai kurang sensitif oleh sebagian kalangan.
Beliau menyebut bahwa jumlah korban tersebut sangat kecil secara statistik, yakni hanya sekitar 0,0006% (atau 0,0007% dalam beberapa kutipan) dibandingkan dengan total 4,5 miliar porsi makanan yang telah didistribusikan.
Dengan kata lain, pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan program mencapai 99,994%.
Pernyataan ini menuai kritik karena “mengecilkan” nilai nyawa dan kesehatan ribuan anak demi keberhasilan statistik sebuah program politik.
Masalah kian pelik ketika kita meninjau aspek legalitas. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis ternyata tidak mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa.
Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perpres tersebut hanya mengatur prosedur pelaporan: SPPG wajib melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika terjadi dugaan keracunan, dan penanggulangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Absennya klausul tanggung jawab pidana yang spesifik dalam Perpres ini menciptakan kesan bahwa regulasi tersebut lebih berfokus melindungi para pejabat dan pelaksana program daripada menjamin keamanan siswa sebagai penerima manfaat.
Hingga kini, meski ribuan siswa terdampak, belum ada langkah hukum konkret terhadap pejabat atau staf MBG di Indonesia yang dianggap bertanggung jawab secara profesional.
Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengenai proses pembentukan regulasi tersebut.
Apakah penyusunan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah melibatkan “partisipasi bermakna” (meaningful participation) dari masyarakat sipil, pakar gizi, dan orang tua siswa?
Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah regulasi yang dibuat tanpa partisipasi publik yang luas dapat dianggap cacat formil.
Jika prosedur pembentukannya mengabaikan transparansi dan masukan masyarakat, maka Perpres tersebut berisiko kehilangan kekuatan hukum mengikat atau bahkan batal demi hukum.
Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah pertaruhan besar.
Tanpa sistem pengawasan yang ketat, perlindungan hukum yang adil bagi korban, dan transparansi anggaran, program ini berisiko menjadi beban sejarah daripada sebuah warisan prestasi.
Kesejahteraan siswa tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka-angka statistik di atas kertas.
Pemerintah harus ingat bahwa satu nyawa siswa yang terancam akibat kelalaian sistem gizi jauh lebih berharga daripada persentase keberhasilan 99% sekalipun.***













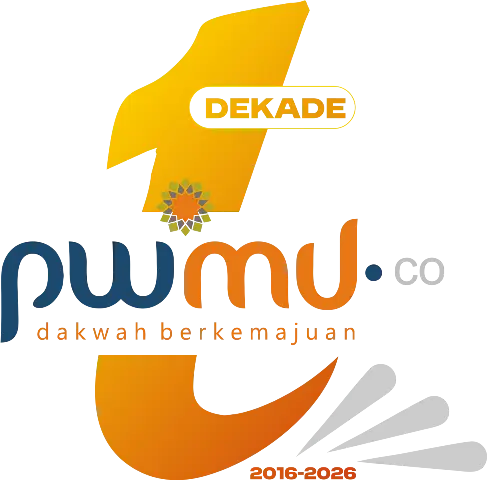

0 Tanggapan
Empty Comments