Gempitanya perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, seharusnya kibaran bendera Merah Putih mendominasi setiap sudut jalan, pekarangan rumah, atap kendaraan-kendaraan. Namun, beberapa daerah — terutama jalur-jalur lintas yang dilalui truk — justru kibaran bendera bergambar tengkorak bajak laut yang berasal dari fiksi One Piece yang mendominasi.
Maraknya penggunaan bendera bergambar tengkorak tersenyum dengan topi jerami—ikon Jolly Roger dalam kisah fiksi One Piece—telah menjadi fenomena yang mencuri perhatian publik. Simbol ini bukan hanya menjadi sorotan, tetapi juga memicu perdebatan panas antara pemerintah, pakar hukum, aktivis, dan masyarakat umum.
Mungkin ada yang melihatnya sekedar bendera anime, tapi ada pula yang memaknai sebagai luapan ekspresif rasa ketidakpuasan yang mendalam. Ada sopir truk yang mengganti Merah Putih pada spion kendaraannya dengan bendera bajak laut itu — seolah membawa pesan “kami lelah dan kecewa” dengan kebijakan yang seperti tak berpihak padanya. One Piece ini seolah menjadi momentum yang tidak lahir dari ruang kosong, tapi tumbuh dari akumulasi rasa frustasi terhadap penerapan hukum yang terasa timpang dan tebang pilih.

Dari Dunia Fiksi ke Jalan Raya
Di jagat fiksi One Piece, bendera Jolly Roger Topi Jerami adalah simbol kru bajak laut yang menolak tunduk pada kekuasaan yang korup. Luffy dan krunya berlayar melawan arus, melawan pemerintahan dunia yang penuh manipulasi dengan satu prinsip: KEBEBASAN. Bagi para penggemar berat One Piece, — bendera itu bukan sekadar kain, tapi representasi dari perlawanan terhadap ketidakadilan, keberanian melawan penindasan, dan tekad mempertahankan martabat.
Ketika simbol ini berpindah dari layar anime ke negeri Indonesia — melalui (misalnya) tiang spion truk —, maknanya berubah menjadi pesan yang mengarah pada dunia realita. Para sopir truk yang menjadi ujung tombak fenomena ini mengaku, pengibaran bendera One Piece adalah cara damai mereka menyuarakan protes. Khususnya terhadap kebijakan ODOL (Over Dimension Overload) yang dapat mematikan mata pencaharian mereka. Bagi mereka, mengapa pemerintah hanya berani tegas pada sopir truk, dan takut bertindak tegas pada pelanggar hukum dari kalangan yang berkuasa? Pertanyaan ini pun hanya menggantung di udara, tanpa ada jawaban yang memuaskan.
Pertanyaannya sekarang, “apakah aksi One Piece ini sebagai bentuk perlawanan yang terencana atau sekadar kekecewaan spontan?”
Secara psikologis, perlawanan lahir dari kesadaran kolektif bahwa ada ketidakadilan struktural yang perlu dilawan. Kekecewaan, di sisi lain, lebih bersifat reaktif akibat ledakan emosi karena perlakuan yang dianggap tidak adil. Fenomena bendera One Piece tampaknya berada di titik tengah antara keduanya.
Dari sisi simbol, ia jelas mengandung unsur perlawanan. Para pengibar memilih ikon “bajak laut” yang secara global diasosiasikan sebagai penentangan terhadap kekuasaan. Namun, dari sisi konteks, fenomena ini lahir mendadak, yang dipicu oleh kebijakan yang dinilai menyudutkan, serta pengalaman sehari-hari dari hukum yang dirasa berat sebelah. Banyak sopir truk yang mengaku tidak punya agenda politik besar; mereka hanya ingin didengar. Dengan kata lain, ini adalah kekecewaan yang mengambil bentuk perlawanan simbolis.
Pemerintah, antara kekhawatiran dan over-reaksi
Pemerintah pun merespons fenomena ini dengan nada reaktif. Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan bahwa pengibaran bendera non-negara di momen kemerdekaan, terutama bila disandingkan atau berada dibawah Bendera Merah Putih merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Beberapa politisi juga menilai aksi pengibaran bendera One Piece berpotensi makar — istilah yang berat, dalam hukum pidana mengacu pada upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aparatur pemerintah pun melakukan razia, mencabuti bendera One Piece dari truk-truk, menginterogasi pengibarnya dengan dalih dimintai keterangan. Tindakan reaktif tersebut justru memicu gelombang kritik baru. Amnesty International Indonesia menyebut tindakan berlebihan aparat itu sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) pun menyatakan bahwa selama Merah Putih tetap dikibarkan sesuai aturan, pengibaran bendera One Piece tidak bisa dianggap pelanggaran.
Mudzakkir, dosen hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) menegaskan bahwa tidak ada unsur makar dalam fenomena ini. Karena aksi tersebut tidak ada indikasi ingin mengganti bendera negara atau merendahkannya. Karena itu, penindakan hukum terhadap para pengibar lebih mencerminkan ketakutan pemerintah terhadap simbol yang menjadi populer, bukan pelanggaran nyata terhadap hukum.
Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan juga para praktisi hukum menilai bahwa hukum tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan untuk membungkam ekspresi publik. Sebaliknya, fenomena aksi ini harus menjadi indikator ketidakpuasan yang jawabannya melalui dialog, bukan represi.
Dimensi Sosial: Kritik terhadap Ketimpangan Penegakan Hukum
Di balik kain hitam bergambar bertengkorak itu, adalah narasi kritis tentang ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Bagi banyak warga, hukum seringkali “terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas”. Sopir truk yang kelebihan muatan bisa segera ditilang atau bahkan dilarang beroperasi, namun kasus besar seperti korupsi triliunan rupiah kerap berjalan lamban atau berakhir dengan vonis ringan. Fenomena ini membentuk persepsi publik bahwa hukum bukan sekadar instrumen keadilan, tetapi juga alat kekuasaan.
Bendera One Piece menjadi media untuk menyuarakan rasa muak itu. Para sopir truk itu seolah menyampaikan pesan: “Jika hukum hanya berpihak pada yang kuat, maka kami memilih menjadi bajak laut.” Meski bersifat metaforis, pesan ini mengguncang karena lahir dari pengalaman nyata ribuan pekerja yang merasa terpinggirkan.
Protes dengan simbol
Penggunaan simbol dari budaya populer sebagai alat protes bukan hal baru. Di Hongkong, misalnya, karakter “Pepe the Frog” sempat menjadi maskot gerakan demokrasi. Di Amerika Latin, topeng “Guy Fawkes” dari film V for Vendetta menjadi lambang anti-korupsi. Dan kini di Indonesia, bendera One Piece yang memikul fungsi serupa.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya pop dapat melintasi batas hiburan dan masuk ke ranah politik. Kekuatan simbol seperti Jolly Roger terletak pada kemampuannya mempersatukan orang-orang dari latar belakang berbeda di bawah satu narasi: “perlawanan terhadap ketidakadilan”. Pemerintah mungkin melihatnya sebagai ancaman, tetapi bagi pengibar, ini adalah bahasa bersama yang mudah dimengerti.
Dalam perspektif komunikasi politik, fenomena bendera One Piece adalah textbook example dari efek Streisand — yaitu ketika upaya menekan atau menghapus sesuatu, berbalik membuatnya justru semakin terkenal. Sebelum aparat melakukan razia, One Piece hanya populer di kalangan sopir truk dan penggemar anime. Namun setelah aparat bertindak reaktif, beritanya pun viral melalui media sosial, menjadi topik utama di televisi, dan menjadi tema penting dalam debat publik nasional.
Alih-alih memadamkan “api perlawanan”, tindakan represif justru meniupnya semakin membesar. Simbol ini pun menjadi memiliki legitimasi moral di mata “korban pembungkaman”. Pengibar pun memperoleh simpati publik yang luas.
Minimnya dialog antara pemerintah dan warga yang terdampak kebijakan menjadi penyulut One Piece. Jika kebijakan, seperti, ODOL atau aturan yang lain menimbulkan reaksi dari rakyat, mestinya ada ruang diskusi yang jujur dan terbuka mencari solusi. Bukan justru memunculkan informasi represif yang tanpa memperdulikan suara mereka sebagai menanggung akibat dari kebijakan. Ketika ruang formal untuk protes tertutup atau diabaikan, wajarlah jika warga mencari jalur kreatif — meski kontroversial — untuk menyuarakan keresahannya.
Maraknya fenomena One Piece atau yang sejenisnya secara tidak langsung memantik peningkatan kesadaran publik tentang ketimpangan penegakan hukum. Sekarang terserah bagaimana sikap pemerintah dalam memberi respon. Jika memilih jalur represif terus-menerus, besar kemungkinan simbol-simbol perlawanan kreatif itu akan terus bermunculan dan bahkan jauh lebih banyak. Sebaliknya, jika pemerintah mengambil inisiatif membuka ruang dialog dan membenahi penerapan hukum, bendera One Piece mungkin akan kembali menjadi sekadar properti cosplay.
Pendek kata, One Piece bukanlah makar, tapi lebih sebagai kritik sosial yang kreatif, damai, dan sah secara moral. Bahkan secara hukum tidak menjadi persoalan, selama tidak melanggar aturan pengibaran bendera negara. Pemerintah seharusnya tidak perlu mengalami paranoia politik, cukuplah dengan dengan introspeksi dan pembenahan. Mengkriminalisasi pengibar bendera One Piece hanya akan menambah jarak antara negara dan rakyatnya.
Simbol bajak laut Topi Jerami ibarat sebuah cermin. Akankah kita memecahkan cermin itu? Atau memperbaiki wajah yang terpantul di dalamnya? ***













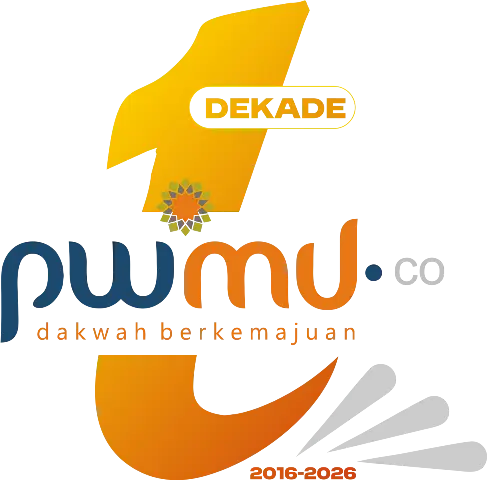

0 Tanggapan
Empty Comments