Hari ini, Selasa (17/2/2026), bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1447 H, langit nusantara seolah menjadi ruang diskusi terbuka dikalangan ulama’ dan para intelektual muslim, dalam menentukan awal bulan Ramadhan, seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan bulan Syawal dan Dzulhijjah.
Di satu kelompok, para perukyat bersiap dengan teleskop dan data-data astronomi, menanti munculnya hilal di ufuk barat. Di kelompok lain, para ahli hisab telah memegang angka-angka presisi tentang posisi, tinggi dan lamanya hilal.
Lalu publik bertanya: mengapa kadang berbeda? Perlukah kita memiliki Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT)? Apakah rukyatul hilal masih relevan di era satelit dan Supercomputer?
Perdebatan ini sering dipersempit menjadi “rukyat versus hisab.” Padahal, di baliknya ada dinamika keilmuan Islam yang panjang dan berakar pada turats (warisan keilmuan klasik), berkembang dalam sains falak, dan menemukan bentuk khasnya di Nusantara.
Tulisan ini mencoba membaca kembali perdebatan tersebut dengan lebih jernih: bukan sebagai pertentangan, melainkan sebagai evolusi metodologi dalam bingkai maqashid syariah dan realitas muslim sosial modern.
Rukyatul Hilal: Teks, Makna, dan Penafsiran
Dasar normatif rukyatul hilal dikenal luas melalui hadis Nabi Saw sebagai berikut:
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ
Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, jika tertutup olehmu (hilal tersebut) maka sempurnakanlah bulan sya’ban menjadi tiga puluh hari” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Secara literal, teks yang termaktub dalam Hadis Shahih al-Bukhari dan Muslim ini, perintahnya jelas: ru’yah (melihat). Namun dalam tradisi keilmuan Islam, teks tidak pernah berhenti pada literalitas.
Para ulama menelaahnya melalui perangkat ushul fiqh: apa makna “melihat”? Apakah ia murni visual-indrawi, ataukah bisa mencakup pengetahuan yang meyakinkan tentang keberadaan hilal?
Dalam mazhab Syafi’i—yang menjadi arus utama di Indonesia—Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa rukyat adalah metode utama yang dipraktikkan pada masa Nabi dan para sahabat.
Namun, beliau juga mencatat keberadaan hisab sebagai ilmu yang telah dikenal. Para ulama klasik memahami bahwa pada masa awal Islam, kemampuan astronomi masyarakat belum merata. Karena itu, rukyat menjadi metode yang paling mudah dan inklusif.
Menariknya, diskusi klasik tidak pernah menutup pintu bagi hisab. Dalam literatur falak klasik—misalnya tabel astronomi seperti Al-Zij al-Sabi’—kita melihat betapa seriusnya para ilmuwan Muslim mengembangkan perhitungan posisi benda langit.
Tradisi ini menunjukkan bahwa hisab bukanlah produk modern yang asing dari Islam, melainkan bagian dari peradaban ilmiah Muslim itu sendiri.
Hisab dalam Turats: Dari Ilmu Bantu ke Metode Penentu
Di masa Abbasiyah, ilmu falak berkembang pesat. Ulama seperti al-Biruni, al-Khawarizmi, dan Ibn al-Shatir mengembangkan model matematis untuk memahami pergerakan bulan dan matahari. Ilmu ini awalnya berfungsi sebagai ‘ulum alat (ilmu bantu), terutama untuk menentukan waktu shalat dan arah kiblat.
Namun seiring waktu, hisab menjadi semakin presisi. Dalam perdebatan fikih, sebagian ulama mulai mempertimbangkan validitas hisab sebagai alat bantu verifikasi rukyat. Di sinilah muncul pendekatan kompromi: rukyat sebagai dasar, hisab sebagai penopang.
Kaidah ushul fiqh yang sering dikutip dalam konteks ini adalah: “Al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh la bi khushush al-sabab” (Yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab).
Dengan demikian, meskipun hadis berbicara tentang “melihat” “bil ‘aini”, maknanya bisa dipahami dalam konteks epistemologis yang lebih luas, yakni memperoleh keyakinan tentang masuknya bulan baru.
Dalam karya ushul seperti Al-Muwafaqat, Imam al-Syathibi menekankan pentingnya maqashid al-shari’ah (tujuan syariat). Jika tujuan syariat adalah kepastian ibadah dan kemaslahatan umat, maka metode yang paling mendekati kepastian ilmiah patut dipertimbangkan.
KHGT: Latar Belakang dan Argumen
Gagasan KHGT muncul dari kebutuhan globalisasi. Umat Islam kini tersebar di berbagai benua, terhubung dalam sistem ekonomi, pendidikan, dan administrasi global. Ketika kalender Hijriyah berbeda antar negara, muncul persoalan administratif, dari penentuan hari libur hingga penyelenggaraan ibadah secara internasional.
KHGT berupaya menetapkan satu tanggal Hijriyah global berdasarkan kriteria astronomi tertentu. Secara ilmiah, posisi bulan dapat dihitung dengan akurasi sangat tinggi. Model visibilitas hilal kini berbasis parameter elongasi, tinggi bulan, umur bulan, dan beda azimut. Artinya, secara saintifik, ketidakpastian visual bisa diperkecil.
Namun, pertanyaannya bukan semata teknis. Apakah unifikasi global selaras dengan turats?. Di sinilah diskursus menjadi menarik. Dalam sejarah fikih, terdapat perbedaan tentang ikhtilaf al-mathali’ (perbedaan tempat terbit bulan).
Sebagian ulama berpendapat bahwa jika hilal terlihat di satu wilayah, maka berlaku untuk wilayah lain. Sebagian lain membatasi pada wilayah tertentu. Artinya, perdebatan global versus lokal sudah ada sejak klasik. KHGT dapat dibaca sebagai pengembangan dari pendapat yang mendukung kesatuan mathla’.
Nusantara: Laboratorium Keilmuan Islam
Indonesia adalah ruang dialog unik antara turats dan modernitas. Dua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mewakili dua pendekatan metodologis.
Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal atau bahkan secara resmi sejak juli 2024 bertepatan dengan 1 Muharram 1446 H mulai menggunakan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) sebagai penerapan awal di internal Persyarikatan melalui Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada Februari 2024 di Pekalongan, serta diluncurkan secara terbuka di di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Rabu (25/6/2025).
Sementara NU juga mengembangkan rukyat dengan dukungan hisab imkan rukyat (kemungkinan terlihat). Keduanya sama-sama merujuk pada turats, namun berbeda dalam penerapannya.
Perbedaan ini sering dibaca sebagai konflik, padahal sejatinya ia adalah dinamika ijtihad. Dalam tradisi Islam, perbedaan ijtihad bukanlah perpecahan aqidah, melainkan kekayaan metodologi.
Di pesantren-pesantren Jawa, kitab falak seperti Sullam al-Nayyirain diajarkan berdampingan dengan fikih klasik. Ini menunjukkan bahwa Nusantara tidak alergi pada sains, tetapi mengintegrasikannya dalam kerangka syariah.
Dalam metodologi kajian keilmuan Islam terdapat istilah yang dikenal dengan “burhani” yakni suatu kaidah memahami nash (teks yang bersumber dari hadits) dilengkapi dengan data-data sains dan hasil observasi.
Rukyatul hilal adalah observasi sebagai implementasi narasi “bayani”, sedangkan hisab adalah teori matematis yang diperoleh dari data-data rukyatul hilal. Keduanya membentuk satu ekosistem epistemik.
Ilmu falak modern telah mengonfirmasi bahwa hilal sangat tipis dan sering tak terlihat meski secara geometris sudah wujud. Di sinilah hisab membantu menjelaskan fenomena kegagalan rukyat.
Maka, pertentangan keduanya sebenarnya adalah dikotomi semu. Yang dibutuhkan adalah integrasi metodologis. Jika kita kembali pada maqashid, menjaga agama (hifz al-din), menjaga persatuan (hifz al-ummah dalam makna luas), dan menciptakan kemaslahatan, maka pertanyaan kuncinya adalah: metode mana yang paling membawa maslahat kolektif?
KHGT menjanjikan keseragaman global, tetapi juga berpotensi mengabaikan tradisi lokal. Atau Rukyatul hilal menjaga simbol kebersamaan melihat langit, tetapi kadang memunculkan perbedaan tanggal. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pendekatan gradual dan dialogis mungkin lebih realistis daripada keputusan sepihak.
Sebagai Ijtihad
Pada akhirnya, persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bukan sekedar soal tanggal. Ia menyentuh identitas, otoritas, dan epistemologi. Turats memberi kita fondasi normative, sains memberi kita alat, dan konteks nusantara memberi kita kearifan sosial.
Islam adalah agama teks, dan konteks sekaligus peradaban ilmu. Dari Basrah hingga kepulauan Nusantara, umat Islam selalu berdialog dengan langit, kadang melalui mata, kadang melalui angka.
KHGT dan rukyatul hilal bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Keduanya adalah bagian dari perjalanan panjang keilmuan Islam. Yang diperlukan bukan polarisasi, melainkan kebesaran hati untuk mengakui bahwa ijtihad selalu bergerak bersama zaman.
Dan mungkin, ketika kita kembali menengadah ke ufuk barat, kita tak hanya melihat hilal, tetapi juga melihat bagaimana Islam terus hidup dalam dialektika keilmuan dan keimanan. (*)













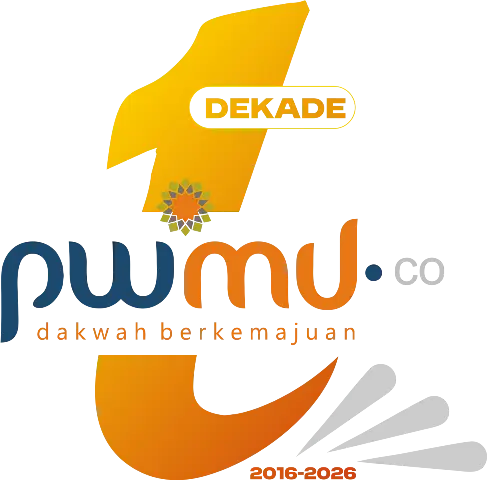

0 Tanggapan
Empty Comments