Pengkhianatan, begitulah mereka menyebutnya. Lalu tudingan, cacian, dan kutukan dilayangkan kepada anak-anak ulama dan para santri yang meninggalkan surau dan menyeberang ke barisan kiri.
Akan tetapi, sebelum keputusan dibuat, adakah yang sungguh-sungguh mendengar kisah di balik langkah itu?
Adakah yang berani memandang mata mereka, yang dulu membaca Al-Qur’an di bawah cahaya lampu minyak, kini justru menulis pamflet revolusi di bawah bayang tiang gantungan?
Mereka tidak kehilangan Tuhannya, tapi kehilangan arah menuju-Nya di dunia yang retak ini.
Tetap saja mereka sangat mencintai Islam, tapi Islam yang mereka temui tinggallah kulit: “indah di kata, tapi kehilangan nyali di kenyataan”.
Di masa penjajahan, ketika tanah-tanah mereka dirampas dan rakyatnya diperas, surau hanya mampu bicara tentang kesabaran, tapi bukan keberanian.
Ulama mengajarkan surga, tapi lupa bahwa bumi pun perlu diselamatkan.
Islam tinggal di sajadah, tidak di sawah; di khutbah, bukan di kebijakan.
Maka ketika ideologi lain datang membawa janji keadilan dan pembebasan, iman pun goyah—bukan karena lemah, tapi karena rindu pada makna yang hidup.
Anak-anak santri itu sedang mencari Tuhan di jalan revolusi.
Mereka menemukan kata-kata yang berdenyut: pembebasan, persamaan, perjuangan kelas.
Kata-kata itu terdengar seperti doa yang lebih nyata daripada ceramah tentang pahala dan akhirat.
Haji Misbach menulis tentang Islam yang melawan kapitalisme, tapi dijauhi karena dianggap terlalu merah.
Tan Malaka, yang masa kecilnya diisi dengan tilawah, tumbuh menjadi buronan karena kata-katanya membakar kesadaran.
D.N. Aidit, anak ulama dari Belitung, tumbuh dengan doa-doa ibunya—namun sejarah menulis namanya dengan tinta merah darah.
Mereka bukan kafir, hanya kecewa karena Islam yang mereka kenal tidak berani berdiri di tengah pertempuran sosial.
Cokroaminoto sudah membaca bahaya itu lebih awal.
Ia memperingatkan: “Barang siapa hendak membangun negara tanpa politik, sama saja dengan membangun tubuh tanpa kepala.”
Tapi siapa yang mendengarkan? Ulama sibuk mengajarkan wudhu sementara bangsa ini kehilangan arah dan martabat.
Masjid ramai dengan doa, tapi sepi dari strategi. Islam berhenti di bibir, tak sempat hidup di medan perjuangan.
Tubuh umat pun berjalan tanpa kepala, dan ideologi lain mengambil alih arah.
Cokroaminoto menatap murid-muridnya tercerai-berai di jalan sejarah.
Soekarno dengan nasionalisme, Muso dengan komunisme, dan Kartosuwiryo dengan Islamisme bersenjata.
Dari rahim perjuangan yang sama, lahir anak-anak yang saling berhadapan di medan sejarah. Semua membawa api, tapi dengan warna yang berbeda.
Kini, seratus tahun kemudian, kita masih mengulang kesalahan yang sama.
Islam masih sibuk pada simbol, sementara keadilan tetap terluka.
Para ulama berdebat tentang fiqh, tapi tak bicara tentang nasib buruh.
Dai-dai ramai memadati televisi, sedangkan rakyat tetap menahan lapar di rumah-rumahnya sempitnya.
Agama kehilangan keberpihakannya, dan iman kehilangan maknanya.
Kita rajin membaca ayat tentang keadilan, tapi bungkam ketika kebenaran dipenjarakan.
Takut kehilangan jamaah, tapi tidak takut kehilangan nurani.
Kita lebih mencintai ketertiban daripada kejujuran.
Janganlah heran jika suatu hari kelak anak-anak pesantren akan kembali pergi — bukan karena benci Islam, tapi karena Islam yang mereka kenal sudah terlalu penakut untuk melawan ketidakadilan.
Mereka akan lebih membaca karya pikiran Karl Marx dengan air mata yang sama, seperti saat dulu mereka membaca Surah Al-Ma’un.
Karena dari pikiran Marx, mereka kembali menemukan jeritan yatim dan miskin yang tak lagi hidup di khutbah-khutbah.
Mereka akan menulis manifesto dengan semangat yang sama ketika dulu mereka menulis doa.
Dan mungkin, dalam hati yang paling sunyi, mereka masih berbisik:
“Ya Allah, aku tidak meninggalkan-Mu. Aku hanya mencari-Mu di jalan yang bisa membebaskan manusia dari penderitaan.”
Bagi mereka, iman sejati tidak hanya berada dalam ruku’ dan sujud. Baginya, iman adalah keberanian menegakkan keadilan, meski ketika itu seluruh dunia menuduhmu sesat.
Dan, selama Islam hanya berhenti pada doa — bukan pada perjuangan—, tubuh umat ini akan terus berjalan tanpa kepala.***




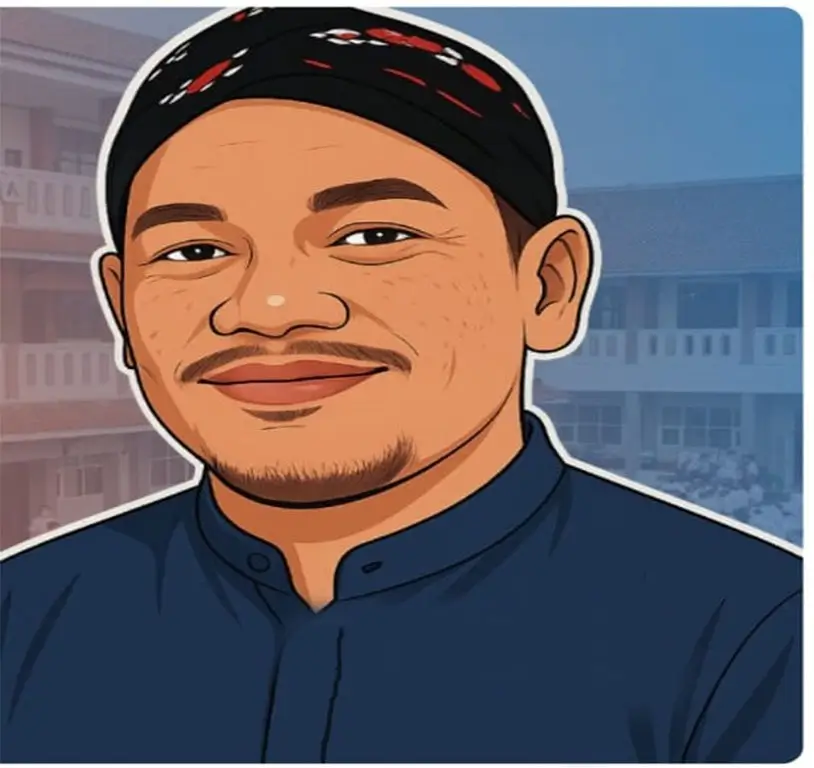








0 Tanggapan
Empty Comments